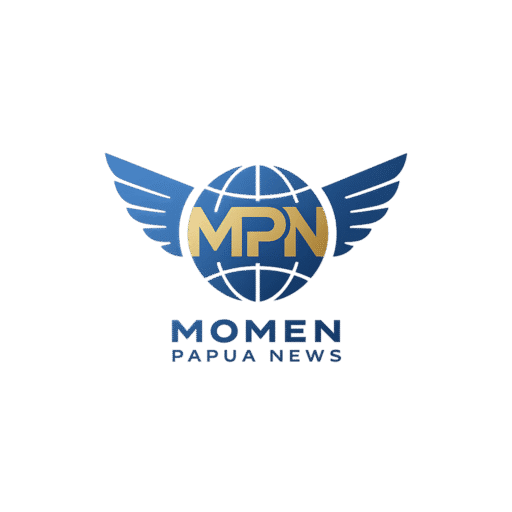Oleh: Jake Merril Ibo (Direktur Pusat Bantuan Mediasi GKI)
ADA tradisi tahunan yang lebih konsisten ketimbang musim hujan, lebih patuh ketimbang jadwal kerja, dan lebih serempak ketimbang upacara 17-an. Tradisi itu bernama: kejar serapan anggaran. Ia bukan sekadar kebiasaan administrasi, tetapi sudah menjadi semacam budaya politik yang merembes sampai ke cara negara memandang rakyatnya: yang penting uang keluar, urusan hasil nanti belakangan.
Setiap tahun kita menonton ulang serial yang sama. Episode awalnya tenang, pertengahan musimnya mulai kacau, dan final season-nya Desember diisi aksi kejar-kejaran yang dramatis. Bedanya, ini bukan tontonan yang menyenangkan. Karena setiap kali final season itu tayang, mutu pembangunan yang seharusnya jadi bintang utama justru jadi korban. Dan korban sesungguhnya bukan tabel, bukan laporan, bukan presentasi PowerPoint. Korban sesungguhnya adalah rakyat.
Tulisan ini mencoba menelanjangi tradisi itu. Dari mana asalnya, kenapa terus berulang, program apa yang biasanya dikebut, siapa yang dirugikan, dan bagaimana seharusnya negara keluar dari siklus tahunan yang merusak ini.
1. Setiap Desember, Negara Kita Mendadak Panik. Negara ini punya kalender tak tertulis yang lebih ditaati daripada kalender resmi: kalender kepanikan anggaran. Begitu masuk Oktober, napas birokrasi mulai pendek. Begitu November bergerak, panik itu naik kelas jadi tradisi. Dan ketika Desember datang, seluruh mesin pemerintahan dari pusat sampai daerah seperti mendadak ikut lomba lari estafet bernama serapan anggaran.
Kalimat yang paling sering terdengar di kantor-kantor pemerintah menjelang tutup tahun bukan “apa yang paling dibutuhkan rakyat?” melainkan “Serapan kita masih rendah”, “Kita harus percepat program”, “Kalau tidak habis, tahun depan dipotong”, “Nanti jadi temuan”, “Ayo kejar realisasi.”
Di atas kertas, semua itu terdengar seperti disiplin pengelolaan uang negara. Tetapi mari kita tanya dengan cara paling jujur, disiplin untuk siapa? Untuk rakyat, atau untuk laporan? Karena realitasnya, setiap akhir tahun kita menyaksikan ritual yang sama. program mendadak dikebut, pengadaan barang melonjak, proyek fisik tancap gas tanpa napas perencanaan, perjalanan dinas “terakhir” kompak meningkat, rapat-rapat dadakan disulap jadi “program percepatan.”
Setelah itu? Banyak yang selesai “secara administratif,” tapi setengah matang secara manfaat. Singkatnya serapan naik, mutu turun, rakyat menanggung akibatnya.
Di titik ini, kita harus berani mengakui bahwa, tradisi tahunan tersebut tidak pernah selesai karena kita berulang-ulang menanam kesalahan yang sama, memandang serapan sebagai tujuan, bukan sebagai alat.
Desember, seharusnya menjadi bulan evaluasi dan perapihan, bukan bulan panik dan kejar-kejaran. Tetapi karena sistem kita membangun ketakutan yang salah, Desember berubah menjadi arena darurat. Dan ketika segala sesuatu dikerjakan dalam keadaan darurat, mutu biasanya jadi barang pertama yang dikorbankan. Ironisnya, kepanikan itu seperti dianggap normal. Seolah-olah negara memang tak bisa bekerja tanpa tekanan deadline. Seolah-olah birokrasi baru bisa jalan, kalau waktu sudah mepet dan ketakutan sudah menempel di dinding. Ini bukan disiplin. Ini kecanduan dan kepanikan.
2. Serapan Anggaran: Antara Angka yang Didewakan dan Substansi yang Ditinggalkan. Serapan anggaran pada dasarnya ukuran sederhana yakni seberapa banyak anggaran yang sudah direalisasikan sesuai rencana. Dalam logika akuntansi, serapan rendah berarti program terlambat atau tidak jalan. Tetapi dalam logika pembangunan, ukuran ini seharusnya selalu ditemani pertanyaan yang lebih penting seperti Serapan untuk program apa?, Program itu relevan atau tidak?, Mutunya bagaimana?, Manfaatnya sampai ke siapa?, Apakah uang itu benar-benar mengubah hidup rakyat?
Masalah serius muncul saat serapan dijadikan agama baru birokrasi, sesuatu yang harus “tinggi” apa pun caranya. Di titik ini, serapan berhenti jadi indikator teknis lalu berubah menjadi alat politik, alat karier, dan alat menekan bawahan. Akhirnya, satu kantor bisa bekerja keras bukan untuk menuntaskan masalah publik, melainkan menuntaskan kecemasan internal: takut anggaran tak habis, takut dipotong, takut dianggap tidak becus. Negara seperti ini bukan negara yang fokus membangun. Ini negara yang fokus menghabiskan. Dan ketika yang dikejar adalah “habis,” maka skala prioritasnya terbalik. Program dibuat bukan karena rakyat butuh, tetapi karena anggaran ada. Kegiatan dipaksakan bukan karena berdampak, tetapi karena harus direalisasikan.
Di sinilah serapan anggaran sering menjadi angka yang tampak gagah di laporan tetapi gagal di lapangan. Serapan 95 persen bisa berarti dua hal yang bertolak belakang: keberhasilan manajemen pembangunan, atau keberhasilan manajemen menghabiskan uang. Sayangnya, di banyak tempat, yang kedua lebih dekat ke kenyataan.
Kita terlalu lama terjebak dalam logika kuantitas: seberapa banyak uang dikeluarkan. Padahal pembangunan berjalan dalam logika kualitas: seberapa besar perubahan yang terjadi. Uang bisa keluar cepat, tetapi perubahan tidak bisa dipaksa lahir lewat kepanikan.
3. Dari “Perencanaan” ke “Kejar Tayang”: Penyakit yang Kita Normalisasikan
Mari kita lihat kronologi penyakit ini secara telanjang.
3.1. Perencanaan Awal Tahun: Rapi di Rapat, Ragu di Lapangan
Di awal tahun, dokumen perencanaan biasanya tebal, presentasi berwarna, target ambisius. Tetapi banyak rencana disusun jauh dari realitas lapangan, terburu-buru untuk memenuhi siklus APBD/APBN, ditulis sebagai formalitas, bukan peta kerja. Maka begitu masuk pelaksanaan, rencana itu terasa seperti kertas bagus yang tidak tahu medan.
Banyak rencana lahir di ruang rapat yang AC-nya dingin, bukan di kampung yang jalannya rusak. Banyak program ditulis demi memenuhi format, bukan memenuhi kebutuhan. Hasilnya seperti peta yang digambar tanpa pernah berjalan di rute yang sebenarnya. Di kertas terlihat lurus, di lapangan ternyata jurang. Perencanaan yang buruk itu punya ciri khas: indikatornya kabur, timeline terlalu optimistis, kebutuhan data tidak lengkap, dan koordinasi antarinstansi cuma hidup di notulen. Di awal, semuanya tampak “jalan.” Tetapi itu hanya karena belum diuji pada kenyataan.
3.2. Tengah Tahun: Banyak Revisi, Sedikit Keberanian
Masuk pertengahan tahun, muncul revisi demi revisi. Ada yang wajar. Tetapi banyak yang terjadi karena studi awal lemah, data dasar tak lengkap, koordinasi antarinstansi buruk, atau program dibuat demi janji politik, bukan kebutuhan publik. Hasilnya, birokrasi jalan sambil memperbaiki ban yang bocor. Wajar kalau tersendat.
Di pertengahan tahun, kita sering mendengar kalimat klasik, “Kita revisi dulu anggarannya.” Revisi bukan masalah, bila yang direvisi adalah strategi menuju hasil yang lebih baik. Masalahnya, revisi sering jadi tanda bahwa sejak awal program tidak punya landasan kuat. Revisi juga sering jadi jalan pintas untuk menyelamatkan muka. Alih-alih mengakui desain salah, kita ganti judul kegiatan, pindahkan pos anggaran, dan beri bungkus baru. Padahal bungkus baru tidak mengubah isi yang rapuh.
3.3. Akhir Tahun: Semua Harus Jalan Sekarang Juga
Lalu, tanpa rasa bersalah, kita tiba di akhir tahun dengan serapan rendah. Dan seperti tradisi, solusinya bukan evaluasi jujur, melainkan percepatan kilat. Kata “percepatan” di negeri ini sering jadi kosmetik untuk menutupi satu hal: keterlambatan yang struktural. Kalau rencana baik, eksekusi lancar, dan data kuat, kita tidak perlu percepatan panik. Percepatan panik adalah tanda bahwa sistem kita tidak sehat dari hulu.
Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, kita menormalkan ketidaksehatan itu. Kita seolah menerima bahwa setiap akhir tahun memang harus panik. Ini mirip orang yang tiap hari merokok lalu merasa wajar batuk tiap pagi. Batuk itu bukan normal tetapi batuk itu gejala sakit. Panik anggaran tiap Desember bukan normal, karena itu adalah gejala kegagalan perencanaan dan manajemen.
4. Program Apa yang Biasanya Dikebut? Dan Kenapa Itu Berbahaya
Setiap Desember, program yang dikebut punya pola yang itu-itu saja.
4.1. Proyek Fisik Kilat
Jalan, ingkungan, drainase, rehab gedung, pengecatan fasilitas publik, pemasangan lampu, dan proyek-proyek kecil-menengah mendadak gencar. Masalahnya, proyek fisik butuh waktu untuk desain teknis, pengukuran, kajian risiko, pengawasan mutu.
Ketika semuanya dikebut di sisa waktu 1–2 bulan, yang terjadi adalah kualitas rendah, pekerjaan asal jadi, risiko ambruk setelah musim hujan pertama, bahkan mark-up lebih mudah terjadi karena pengawasan melemah.
Kita sering lihat jalan mulus yang baru diaspal Desember… lalu Maret sudah retak seperti janji-janji kampanye.
Proyek fisik itu bukan sekadar mengejar selesai. Ia menuntut ketepatan teknik. Jalan bukan hanya harus jadi, tetapi harus awet. Drainase bukan hanya harus dibangun, tetapi harus bekerja saat hujan datang. Rehab sekolah bukan hanya harus tampak rapi di foto, tetapi harus aman dan nyaman untuk anak-anak.
Ketika proyek dipercepat secara brutal, yang hilang bukan cuma waktu, melainkan kesempatan untuk berpikir. Dan pembangunan yang kehilangan kesempatan berpikir biasanya melahirkan kesalahan yang mahal.
4.2. Pengadaan Barang Massal
Laptop, printer, alat kantor, meubel, kendaraan dinas, bahkan alat kesehatan dibeli masif. Masalahnya, pengadaan kilat sering berujung pada spesifikasi dipaksa “yang penting ada,” vendor yang tidak siap, harga tidak kompetitif, barang numpuk di gudang.
Lebih parah, pengadaan menjadi cara cepat “menyerap” tanpa pertanyaan: apakah barang ini benar-benar dibutuhkan?
Di banyak kantor, akhir tahun adalah momentum “belanja besar.” Kalau program fisik belum siap, pengadaan barang jadi jalan pintas untuk menyerap sisa anggaran. Dari kursi, meja, komputer, sampai kendaraan, semua bisa dibuat “kebutuhan mendesak” dalam satu malam rapat internal. Padahal, barang yang dibeli tanpa kebutuhan nyata adalah uang publik yang dipindahkan dari rekening negara ke gudang yang tak berguna. Ia mungkin membuat serapan naik, tetapi tidak membuat layanan publik naik.
4.3. Pelatihan dan Bimtek Dadakan
Seminar, workshop, bimtek, sosialisasi, studi banding — ini “menu wajib” akhir tahun. Masalahnya, banyak kegiatan ini dibuat untuk serapan, bukan untuk transfer keahlian, unggul di nota dinas, lemah di dampak, berakhir dengan sertifikat, bukan perubahan kapasitas.
Kita terlalu sering menghasilkan tumpukan sertifikat, bukan tumpukan kemampuan, kapasitas dan kapabilitas.
Bimtek dan pelatihan seharusnya menjadi investasi SDM. Tetapi karena dikebut, ia sering jadi wisata birokrasi berkedok peningkatan kapasitas. Materi kadang umum, peserta kadang tidak tepat, tindak lanjut kadang nihil. Setelah pulang, Laporan selesai, foto terunggah, sertifikat dibagikan. Tapi pekerjaan di kantor tetap sama, layanan publik tidak berubah.
4.4. Perjalanan Dinas “Terakhir”
Akhir tahun jadi musim migrasi birokrasi: rapat koordinasi, konsultasi, monitoring, evaluasi di luar daerah. Masalahnya, perjalanan dinas sering menjadi cara cepat menghabiskan sisa anggaran, kegiatan yang minim output nyata, ladang pemborosan terselubung. Rakyat hanya melihat pejabat mondar-mandir. Tapi tak melihat layanan publik ikut membaik.
Tidak semua perjalanan dinas buruk. Ada yang perlu untuk koordinasi dan belajar. Tetapi akhir tahun punya pola khas: perjalanan dinas “tiba-tiba perlu” karena anggaran harus segera terserap. Rapat bisa dilakukan daring? Tetap jalan ke luar kota. Konsultasi bisa lewat surat? Tetap terbang. Monitoring bisa di wilayah sendiri? Tetap dibawa ke hotel. Ini bukan semangat kerja. Ini semangat menghabiskan.
- Kenapa Tradisi Ini Terus Terjadi?
Kalau penyakit ini terjadi sekali dua kali, kita bisa bilang “kecelakaan.” Tapi kalau terjadi setiap tahun, itu sistem. Setidaknya ada lima akar masalah.
5.1. Logika “Anggaran Harus Habis”
Di banyak instansi, ada keyakinan tak tertulis kalau anggaran tidak habis, dianggap gagal. Padahal, dalam logika publik yang penting bukan habis, tetapi tepat. Ada uang yang tidak habis karena efisiensi, dan itu justru prestasi.
Tapi birokrasi sering disetir mental takut: takut dipotong, takut disalahkan, takut dianggap tidak bekerja. Maka serapan jadi target mutlak.
Ini bagian paling tragis. Kita menghukum efisiensi. Kita curiga pada penghematan. Kita seakan berkata: “Kalau kamu tidak habiskan anggaran, kamu malas.” Padahal bisa saja tidak habis karena lebih efisien atau karena programnya memang tidak layak dipaksakan.
Ketakutan ini seperti cambuk yang membuat birokrasi memilih jalan paling aman: habiskan saja.
5.2. Sistem Penganggaran Tahunan yang Kaku
Anggaran pemerintah bekerja dalam siklus tahunan. Yang tidak terpakai, kalau tidak diatur dengan baik, tidak bisa pindah otomatis ke tahun depan.
Kekakuan ini mendorong perilaku “pakai sekarang saja sebelum hangus”, “realisasikan apa pun sebelum tutup buku.”
Bukan salah siklus tahunan semata, tapi salah cara kita memperlakukan siklus itu. Sistem tahunan bisa sehat kalau manajemennya disiplin dan ada mekanisme carry-over yang jelas untuk program multi-tahun. Tapi tanpa itu, uang yang seharusnya dipakai tepat waktu berubah jadi uang yang dipakai karena takut hangus.
5.3. Perencanaan yang Lemah dari Awal
Banyak serapan rendah bukan karena malas, tapi karena data awal tidak valid, desain program asal comot, kapasitas perencana rendah, target tak realistis. Kita sering menulis rencana tanpa memahami medan. Akhirnya pelaksanaan tersandung.
Perencanaan lemah itu seperti membangun rumah tanpa pondasi. Begitu hujan pertama datang, rumahnya miring. Dan Desember adalah hujan pertama bagi prematuritas perencanaan.
5.4. Tender dan Pengadaan yang Lambat
Proses pengadaan yang panjang sering terlambat dimulai. Banyak instansi baru tender di pertengahan tahun, bahkan menjelang akhir. Begitu tender selesai, waktu tinggal sedikit. Maka proyek dikebut.
Ini bukan sekadar masalah aturan, tapi manajemen waktu yang buruk dan minimnya disiplin perencanaan teknis.
Tender lambat bukan nasib. Itu akibat keputusan manajerial: menunda, ragu, takut, atau tidak siap sejak awal. Lalu ketika sudah terlambat, kita menutupnya dengan kata sakti: “percepatan.”
5.5. Budaya Birokrasi yang Anti Evaluasi
Sistem kita lebih suka menutup masalah, menghindari rasa malu, menghindari kritik daripada mengakui kekeliruan dan memperbaiki desain.
Akhirnya, setiap tahun kita masuk ke lubang yang sama karena tidak pernah membangun jembatan untuk keluar.
Budaya anti-evaluasi ini membuat penyakit serapan kilat hidup terus. Karena tidak ada mekanisme belajar. Tidak ada keberanian mengatakan: “Program ini salah desain.” Tidak ada ruang untuk memperbaiki di awal. Yang ada hanya semangat “jalan terus dulu,” lalu Desember panik bersama.
- Mutu yang Dikurbankan Itu Mutu Siapa?
Ketika mutu proyek turun, yang rugi bukan pejabat yang tanda tangan. Yang rugi adalah rakyat. Jalan rusak? rakyat yang jatuh, ekonomi kampung yang tersendat. Sekolah direhab asal jadi? Anak-anak belajar dalam ruang dingin dan bocor. Alat kesehatan dibeli tanpa pelatihan? Pasien yang tidak tertolong. Pelatihan dadakan tanpa dampak? Masyarakat tetap tak terlayani karena SDM tidak naik kelas.
Mutu yang dikorbankan bukan mutu abstrak. Itu mutu hidup manusia. Dan itu yang membuat tradisi serapan kilat bukan sekadar masalah administrasi, tetapi masalah moral.
Serapan kilat sering dibicarakan dalam bahasa teknis seolah tidak berhubungan dengan etika. Padahal ketika kita memilih menghabiskan anggaran tanpa memikirkan mutu, kita sedang membuat keputusan moral: mendahulukan laporan daripada kemanusiaan manusia.
- Tradisi Serapan Kilat Melahirkan Dua Monster: Pemborosan dan Korupsi
Tidak semua percepatan berujung korupsi, tetapi percepatan panik menyediakan karpet merah bagi dua monster ini.
7.1. Pemborosan yang Dianggap Normal
Ketika serapan dijadikan dewa, pemborosan jadi ritual rapat di hotel mahal, pengadaan barang yang tak terpakai, pembangunan yang tidak mendesak, program yang hanya mengulang kegiatan tahun lalu.
Pemborosan menjadi “wajar” karena dibungkus kata suci: “realisasi.” Kita tidak lagi merasa bersalah ketika menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak prioritas. Karena pikiran kita sudah dicuci oleh logika serapan: “yang penting keluar dulu.”
7.2. Korupsi yang Disamarkan oleh Kejar Waktu
Kejar waktu melemahkan kontrol pemeriksaan mutu tak detail, verifikasi dokumen longgar, negosiasi vendor lebih gelap, pengawas lapangan tak sempat cek ulang.
Korupsi paling mudah tumbuh di ruang yang sesak waktu dan minim pengawasan. Desember menyediakan ruang itu tiap tahun. Jika kita ingin jujur, banyak korupsi berawal dari celah kecil yang diberi nama percepatan. Ketika waktu mepet, prosedur menjadi elastis. Ketika prosedur elastis, integritas diuji. Ketika integritas diuji tanpa kontrol kuat, monster masuk lewat pintu belakang.
- Lalu, Apakah Serapan Tinggi Itu Buruk?
Tidak. Serapan tinggi bisa sangat baik kalau dicapai lewat perencanaan matang dan eksekusi berkualitas. Masalahnya bukan “serapan tinggi,” masalahnya adalah serapan tinggi yang panik, serapan tinggi yang tak relevan, serapan tinggi yang mengorbankan mutu.
Serapan seharusnya mengekor manfaat, bukan manfaat mengekor serapan. Serapan tinggi yang sehat terasa tenang, tidak perlu dramatis, tidak perlu kebut-kebutan. Pembangunan berjalan lewat ritme yang konsisten dari Januari sampai Desember. Kalau serapan tinggi hanya muncul setelah panik, itu bukan prestasi, itu sekadar efek samping dari ketakutan.
9. Apa Program yang Layak Dipercepat di Akhir Tahun?
Kalau kita realistis, ada program yang memang boleh dipercepat karena urgensinya tinggi dan sifatnya rutin, jelas kebutuhannya, risikonya rendah, manfaatnya cepat dirasakan. Contohnya: Perawatan rutin jalan/jembatan yang sudah punya desain jelas. Pengadaan obat dan layanan kesehatan mendesak. Program padat karya untuk menyerap tenaga lokal saat ekonomi lesu. Rehabilitasi kecil fasilitas publik yang sudah terukur. Dukungan bencana/kerusakan yang memang tidak bisa menunggu.
Kuncinya: percepatan yang berbasis kebutuhan nyata, bukan berbasis sisa anggaran. Percepatan di akhir tahun boleh saja, tetapi harus selektif dan etis. Ia harus menolong publik, bukan menolong tabel serapan.
- Program Apa yang Tidak Boleh Dikebut?
Ada juga program yang seharusnya haram dikebut karena berisiko tinggi. Proyek infrastruktur besar tanpa studi matang. Pengadaan barang mahal dan kompleks. Program baru tanpa data dasar dan pilot. Pembangunan yang memotong ruang hidup masyarakat tanpa konsultasi. Kegiatan seremonial yang manfaatnya tidak jelas.
Kalau program ini dipaksakan di akhir tahun, hasilnya bukan percepatan, tapi kecelakaan kebijakan. Kecelakaan kebijakan itu mahal. Ia tidak hanya menghabiskan uang, tetapi merusak kepercayaan. Dan memperbaiki kepercayaan jauh lebih sulit ketimbang memperbaiki jalan rusak.
- Jalan Keluar yang Nyata: Bangun Sistem, Bukan Tradisi Panik
Kita tidak butuh slogan baru. Kita butuh sistem baru. Setidaknya empat pembenahan besar.
11.1. Jadikan Serapan sebagai Indikator Pendukung, Bukan Target Utama
Ukuran utama keberhasilan harus bergeser ke mutu output, manfaat outcome, kepuasan layanan publik. Serapan tetap penting, tapi posisinya di belakang kualitas. Dengan begitu, birokrasi tidak akan lagi mengejar angka secara membabi buta. Mereka akan mengejar perubahan, lalu serapan akan mengikutinya secara alami.
11.2. Perencanaan Berbasis Data dan Kebutuhan Warga
Bukan perencanaan berbasis copy-paste tahun lalu, keinginan elit, proyek titipan.
Data lapangan harus jadi fondasi. Musrenbang harus bermutu, bukan formalitas. Kalau program lahir dari kebutuhan riil, ia tidak butuh dipaksa di akhir tahun. Ia akan jalan sendiri karena memang diperlukan.
11.3. Mulai Tender Lebih Awal dan Disiplin Jadwal
Jika tender dimulai Januari–Februari, proyek punya waktu cukup untuk kerja tenang, pengawasan ketat, mutu terjaga. Keterlambatan tender adalah akar serapan panik.
Negeri ini tidak kekurangan aturan. Negerinya yang kekurangan disiplin manajemen.
11.4. Beri Ruang Efisiensi Tanpa Hukuman
Instansi yang tidak menghabiskan anggaran karena efisiensi tidak boleh dianggap gagal. Harus ada mekanisme carry-over yang sehat atau penghargaan efisiensi yang jelas. Tanpa itu, birokrasi akan terus memilih “habiskan” daripada “hemat.” Kita perlu menyatakan secara tegas: menghemat anggaran publik adalah prestasi, bukan dosa.
- Ini Bukan Sekadar Soal Uang. Ini Soal Cara Negara Menghargai Rakyat
Ritual serapan akhir tahun adalah cermin: apakah negara benar-benar bekerja untuk warga, atau bekerja untuk laporan? Kalau setiap tahun pembangunan diburu-buru agar “habis anggaran,” itu sama saja mengaku:
“Yang penting uang keluar, soal hasil nanti urus belakangan.” Padahal rakyat hidup di depan, bukan di belakang. Rakyat tidak makan presentasi serapan. Rakyat tidak bisa menyeberang lewat tabel realisasi. Rakyat tidak sembuh karena grafik penyerapan.
Rakyat butuh layanan yang benar, jalan yang awet, sekolah yang hidup, puskesmas yang berfungsi, ekonomi yang bergerak.
Mutu pembangunan adalah cara paling konkret yang seharus sebagai negara berkata: “Kami menghargai hidupmu.” Dan sebaliknya, pembangunan yang asal jadi adalah cara paling telanjang sebagai negara berkata: “Kami lebih menghargai laporan daripada hidupmu.”
- Penutup: Sudahi Tradisi Tahunan Ini, Atau Kita Sendiri yang Akan Disudahi Sejarah
Kita bisa terus memelihara tradisi panik ini sampai kapan pun. Tapi ada harga yang selalu dibayar pembangunan jadi tambal sulam, uang publik terbuang, mutu layanan merosot, ketidakpercayaan rakyat tumbuh, korupsi dapat panggung.
Dan yang paling menyedihkan adalah setiap tahun kita mengulang kesalahan yang sama seolah itu kodrat, padahal itu pilihan. Pilihan untuk tidak berbenah. Pilihan untuk menjadikan serapan sebagai tujuan. Pilihan untuk mengorbankan mutu.
Kalau negara ini ingin dewasa, maka Desember tidak boleh lagi jadi bulan panik. Desember harus jadi bulan evaluasi jujur: apa yang gagal, kenapa gagal, dan bagaimana memperbaikinya dari hulu ke hilir. Karena pembangunan yang baik dan benar tidak lahir dari kejar tayang. Ia lahir dari rencana yang waras, kerja yang disiplin, pengawasan yang ketat, dan keberpihakan pada mutu hidup rakyat.
Kalau tidak, kita akan terus menyaksikan ironi ini berulang: serapan tinggi di laporan, tapi mutu rendah di kampung-kampung. Dan suatu saat, rakyat akan berhenti percaya pada negara yang setiap tahun sibuk menghabiskan uang, tapi lupa membangun kehidupan.
Tradisi tahunan ini tidak akan berhenti hanya karena kita menjadikannya sebagai dewa. Ia akan berhenti ketika kita mengubah cara berpikir yang menjadi akar: dari “bagaimana menghabiskan anggaran” menjadi “bagaimana menyelesaikan masalah rakyat.”
Jika negeri ini bisa menaklukkan kebiasaan panik yang ia pelihara sendiri, maka kita akan melihat pembangunan yang lebih waras: bukan pembangunan yang lahir dari ketakutan, tetapi pembangunan yang lahir dari kesadaran. Dan saat itu terjadi, serapan bukan lagi lomba akhir tahun. Ia menjadi bagian wajar dari kerja negara yang normal: bekerja sejak awal, bekerja dengan mutu, bekerja untuk manusia.