PEMERINTAH kembali membentuk lembaga baru untuk “mempercepat pembangunan” di Papua. Hal ini tentu sangat diapresiasi. Namun, di balik niat baik itu, muncul tanda tanya besar: apakah Papua benar-benar butuh struktur kelembagaan formal baru? Atau justru pemerintah yang perlu meningkatkan empatinya terhadap suara orang Papua? Sekurang-kurangnya tujuh hal yang menjadi catatan penting terhadap pemerintah pusat.
1. Tumpang Tindih Lembaga, Tumpang Tindih Suara
Selama dua puluh tahun terakhir, Papua tampak dijadikan arena uji coba berbagai kebijakan pemerintah pusat. Setiap kali persoalan muncul, pendekatan yang diambil nyaris seragam, membentuk lembaga baru. Setelah kehadiran UP4B di masa Presiden SBY, dibawah Presiden Joko Widodo, membentuk Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dan kembali lagi dibawah Pemerintahan Presiden Prabowo dibentuk dan dikukuhkan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP2OKP).
Meski BP3OKP dibentuk pada tahun 2022 dengan mandat mempercepat pembangunan berbasis Otonomi Khusus, hingga kini lembaga tersebut belum menorehkan hasil yang signifikan. Fokus kerjanya masih didominasi oleh upaya membangun koordinasi antar provinsi di Tanah Papua. Namun, pemerintah kembali menghadirkan KEP2OKP dengan tanggung jawab yang relatif sama.
2. Krisis Pendengaran Pemerintah
Papua sejatinya tidak kekurangan struktur pemerintahan, sebab yang sesungguhnya hilang adalah kemampuan pemerintah untuk mendengar.
Aspirasi rakyat Papua terus bergema dari mimbar gereja, ruang kuliah, kampung adat, forum perempuan, hingga media lokal tetapi suara itu jarang tiba secara utuh di telinga para pengambil keputusan di Jakarta.
Masalahnya bukan karena rakyat diam, melainkan karena suara mereka tersesat di antara lapisan birokrasi. Sebelum sampai ke Presiden dan Wakil Presiden, aspirasi itu harus melewati sederet filter: kementerian, staf ahli, dan lembaga-lembaga baru yang mengaku dan/atau dibentuk “mewakili” Papua dan untuk percepatan Pembangunan Papua.
Akhirnya, didapati yang tersisa bukan lagi jeritan nurani rakyat, melainkan gema administratif atau laporan teknokratis yang dingin, kehilangan roh kemanusiaan. Ketika suara itu akhirnya terdengar di pusat kekuasaan, ia bukan lagi suara Orang Asli Papua (OAP), tetapi versi yang telah “diedit” oleh tafsir politik dan kepentingan birokrasi.
3. Rakyat Tidak Butuh Komite, Mereka Butuh Komitmen
Ketika rakyat Papua berbicara tentang pendidikan yang mahal, rumah sakit tanpa obat, atau jalan yang rusak, mereka tidak sedang meminta dibentuknya lembaga baru. Mereka meminta pemerintah hadir dengan hati, bukan sekadar hadir dengan sederetan nama dan jabatan.
KEP2OKP hanya akan menjadi simbol tambahan jika tidak diiringi dengan kesediaan mendengarkan rakyat secara langsung. Jika tugas utamanya hanyalah menambah tumpukan rapat, laporan, dan dokumen koordinasi, maka Papua tidak akan bergerak.
Jadi yang berubah hanya struktur, bukan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan Orang Asli Papua.
Orang Papua dengan Sejarah penderitaannya, tidak sedang menunggu dibentuknya lembaga baru untuk menghapus air mata kepedihan. Orang Papua menunggu komitmen nyata untuk mendengar dan hadir bersama mereka dalam ruang dialog.
Sudah terlalu sering masalah Papua dijawab dengan surat keputusan, badan percepatan, dan komite-komite baru. Tetapi, dari lembaga-lembaga itu, seberapa banyak yang benar-benar memahami denyut hati Orang Papua di pegunungan, di pesisir, di lembah-lembah, di Sungai-sungai besar dan pulau-pulau jauh yang belum tersentuh sinyal?
Pemerintah seharusnya mengambil langkah yang lebih sederhana namun bermakna, yakni duduk dan mendengar. Bertemu tokoh adat di honai atau para-para adat mereka. Mendengarkan para pemimpin gereja dan agama berbicara tentang kepenatan, luka, rekonsilasi dan harapan umat. Memberi ruang bagi perempuan Papua untuk menyampaikan suara yang selama ini tenggelam didominasi kaum patriarki. Mengajak anak-anak muda berdiskusi tanpa stigma dan kecurigaan. Melihat Bintang kejora sebagai simbol perjuangan keadilan, bukan sebagai ancaman bagi disintegrasi bangsa.
Itulah langkah yang bijak dan berani, bukan membentuk badan-badan baru yang saling tumpang tindih, tetapi pemerintah perlu berani mewujudkan kehadiran yang sejati.
Wakil Presiden yang memimpin Badan/Komite Percepatan Pembangunan Papua juga jika ingin benar-benar berbicara tentang Papua, maka ia harus berbicara langsung dengan rakyat Papua, bukan hanya menerima laporan-laporan dari Badan/Komite yang paksakan sebagai katalisator. Berbicara langsung itu bukan melalui perantara. Sejujurnya Orang Papua tidak membutuhkan lembaga percepatan. Papua membutuhkan kehadiran yang mendengar, komitmen yang tulus, dan keberanian untuk berdialog tanpa jarak.
4. Suara yang Berlekuk-Lekuk
Ungkapan “suara berlekuk-lekuk” melukiskan betapa perjalanan aspirasi rakyat Papua penuh liku. Dari tingkat kampung ke Tingkat distrik menuju kabupaten, lalu ke provinsi dan kementerian, pesan rakyat itu kerap berubah bentuk. Setiap jenjang birokrasi memproduksi tafsir dan kepentingannya sendiri, hingga makna awalnya yang natural perlahan mengabur.
Ketika suara itu akhirnya tiba di meja Presiden dan wakil Presiden, yang tersisa bukan lagi ungkapan jujur dari suara hati rakyat Papua, melainkan versi yang sudah dipoles oleh birokrasi yang tumpeng tindih dengan rapi di atas kertas, tapi kehilangan rohnya.
Akibatnya, banyak kebijakan yang lahir dari proses itu terasa melayang di udara: rumah dibangun di tempat yang tak berpenghuni, sekolah berdiri tanpa guru, dana Otsus mengalir tanpa arah yang pasti.
Semua kekeliruan itu berpangkal pada satu hal mendasar: suara rakyat Papua tak pernah sampai dalam bentuk aslinya.
5. Saatnya Pemerintah Menjadi Mediator, Bukan Membentuk Struktur Baru
Ketika Papua butuh didengar, pemerintah seharusnya menjadi mediator, bukan membentuk badan-badan yang saling tumpang tindih. Mediator berarti hadir untuk mendengarkan, berempati, memahami, dan menjembatani, bukan sekadar mengatur dan memerintah.
Dalam konteks ini, langkah pemerintah membentuk KEP2OKP justru memperlihatkan sinyal kebingungan struktural. Alih-alih menata komunikasi yang rusak antara rakyat Papua dan pemerintah pusat, yang dilakukan justru menambah simpul baru dalam rantai birokrasi yang sudah kusut.
Lebih jauh lagi, fenomena ini mencerminkan sinyal politik di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, yang mana kebijakan tentang Papua tetap ditempuh melalui pendekatan struktural, militerisasi, bukan dialogis, maka dalam hal ini menandakan bahwa Presiden Prabowo belum memiliki niat kuat untuk benar-benar mendengar Suara Orang Asli Papua.
Papua tidak butuh tambahan lembaga; Papua butuh jembatan komunikasi yang autentik antara pusat dan rakyat di akar rumput.
6. Mendengar dengan Hati, Bukan Dengan Mikrofon
Percepatan pembangunan di Papua tidak akan terwujud lewat pembentukan lembaga baru, melainkan melalui kemauan tulus pemerintah untuk mendengar dengan hati. Jadi yang dibutuhkan bukan struktur tambahan, tetapi kepekaan untuk mendengarkan suara masyarakat tanpa prasangka.
Dengarkan para tetua adat tanpa curiga, dengarkan perempuan Papua tanpa menempatkannya sebagai pelengkap, dan dengarkan kaum muda tanpa lebih dulu memberi label “provokator.”
Apabila pemerintah sungguh ingin KEP2OKP menjadi berbeda dari sebelumnya, maka langkah pertama bukan merancang program, tetapi membuka telinga dan hati untuk mendengar langsung dari rakyat.
Papua tidak sedang menunggu penjelasan panjang lebar dari pusat, Papua hanya ingin didengarkan, apa adanya.
7. Kewenangan Gubernur Sudah Cukup, Papua Tidak Butuh Lembaga Baru
Saya percaya, enam gubernur di Tanah Papua, dari Papua Barat Daya hingga Papua Pegunungan, adalah putra-putra terbaik Papua. Mereka lahir, besar, dan mengabdi di tanah ini; mereka mengenal medan, mengenal rakyat, dan memahami denyut nadi sosial yang tak bisa dibaca lewat laporan birokrasi.
Jika pemerintah pusat benar-benar memberi mereka kepercayaan penuh dan kewenangan utuh, tanpa intervensi dan tanpa harus menunggu keputusan dari badan atau komite baru, saya yakin mereka sanggup membawa Papua ke arah yang hebat.
Masalah pembangunan di Papua bukan karena kurangnya struktur, tetapi karena terlalu banyak lapisan yang membuat keputusan menjadi lamban dan tidak efektif. Sejak otonomi khusus diberlakukan, kewenangan gubernur sebenarnya sudah luas, baik dalam pengelolaan anggaran, prioritas pembangunan, maupun pembinaan sosial. Namun setiap kali muncul masalah, pemerintah pusat justru membentuk lembaga baru, seolah-olah gubernur tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya.
Padahal, gubernur adalah pemimpin politik dan sosial tertinggi di daerah, bukan sekadar pelaksana teknis. Mereka memiliki legitimasi rakyat melalui pemilihan, dan secara hukum memiliki perangkat birokrasi yang lengkap.
Membentuk badan-badan baru di atas kewenangan mereka hanya menimbulkan kebingungan, memperbanyak koordinasi tanpa hasil, serta mereduksi martabat pemerintahan daerah.
Papua tidak butuh KEP2OKP; Papua butuh kepercayaan pemerintah pusat. Percaya bahwa para gubernurnya mampu memimpin. Percaya bahwa, mereka bisa membangun sinergi lintas wilayah tanpa dikawal oleh lembaga pusat yang seringkali tidak memahami konteks lokal.
Percaya bahwa keberhasilan Papua lahir dari kepemimpinan yang dekat, bukan dari instruksi yang jauh.
Memberikan ruang kepada enam gubernur untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab adalah bentuk penghormatan terhadap Otonomi Khusus sehingga Otonomi Khusus bukan slogan, tapi praktik nyata dari desentralisasi yang bermartabat.
Pemerintah pusat harus belajar bahwa memperbanyak badan bukan solusi; memperbanyak kepercayaan adalah kunci. Biarlah enam gubernur Papua memimpin dengan cara mereka, karena mereka tidak hanya mengerti tanah ini, tetapi juga memiliki hati dan tahu cara untuk membangun Papua dan orang-orangnya menjadi lebih baik.
Masalah utama Papua bukanlah kekurangan lembaga, melainkan krisis kepemimpinan yang mampu mendengar dengan hati — listening leadership. Terlalu sering setiap persoalan dijawab dengan membentuk struktur baru, bukan dengan membuka ruang dialog yang sejati.
Akibatnya, arah pembangunan berjalan seperti gema dalam ruang kosong: berisik di atas, hening di bawah.
Papua tidak membutuhkan Komite tambahan, yang dibutuhkan adalah komitmen untuk benar-benar mendengarkan rakyatnya. Papua tidak menagih janji pembangunan, tetapi menunggu kesediaan pemerintah untuk mendengar tanpa penyaring, tanpa tafsir, tanpa jarak mendengar sebagaimana adanya.
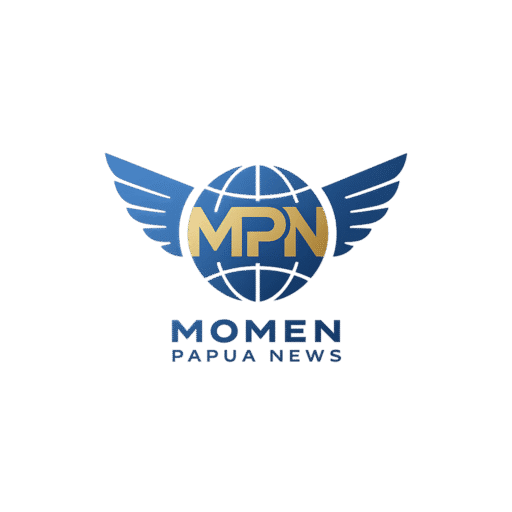















Setuju 👍🏼
Papua butuh di dengarkan segala Aspirasi rakyat.