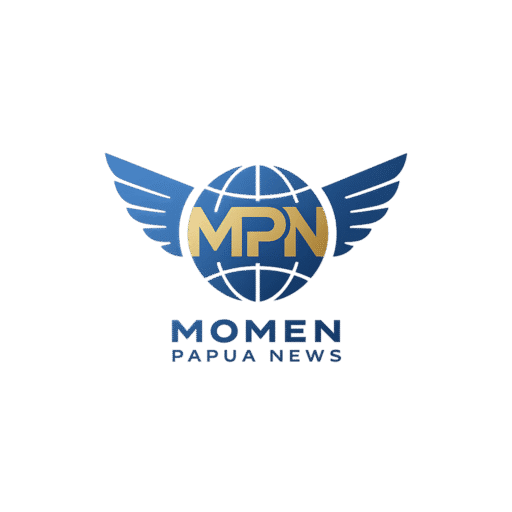SEJAK puluhan tahun, Tanah Papua seolah berdiri di antara dua jurang, kemajuan dan luka lama. Di satu sisi, pembangunan dikejar dengan jargon “keadilan dan kesejahteraan”; di sisi lain, sejarah yang terdistorsi dan kekerasan yang berulang masih menjadi bayangan yang tak kunjung padam. Pertanyaannya sederhana namun tajam, mengapa Papua masih terus bergulat dengan luka yang sama?
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang kini menjadi bagian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sejak awal telah mengurai empat akar masalah Papua, yakni :
1. Distorsi sejarah kebenaran yang tak pernah tuntas diakui.
2. Kekerasan terhadap Orang Asli Papua (OAP) yang berlangsung dalam berbagai bentuk, dari fisik hingga struktural.
3. Kegagalan pembangunan yang gagal menyentuh akar kebutuhan masyarakat adat.
4. Marginalisasi yang menyingkirkan OAP dari ruang sosial, politik, dan ekonomi di tanahnya sendiri.
Untuk menjawab empat akar persoalan itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sesungguhnya telah memberi jalan hukum.
Pada Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46, secara tegas disebutkan perlunya dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Dua lembaga ini adalah mekanisme kunci untuk membuka ruang kebenaran sejarah dan menegakkan keadilan atas kekerasan yang menimpa OAP.
Sementara itu, untuk menjawab dua akar masalah lainnya kegagalan pembangunan dan marginalisasi undang-undang ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021. Regulasi ini memberi dasar hukum bagi daerah untuk menyusun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berpihak pada perlindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan OAP.
Namun, persoalannya bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada kemauan politik untuk melaksanakannya secara sungguh-sungguh.
Sebelum menjadi anggota DPR Papua, pada tahun 2015, saya menulis naskah buku berjudul Penegakan HAM di Tanah Papua, Perspektif UU Otsus Papua. Tuhan baik, sebab melalui proses seleksi, saya kemudian diangkat menjadi anggota DPR Papua lewat mekanisme kursi pengangkatan yang dikenal sebagai kursi Otsus.
Sebagai anggota DPR Papua, saya menggunakan hak inisiatif untuk menyusun dan mengajukan dua rancangan regulasi penting :
1. Raperdasus tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
2. Raperdasus tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM—lengkap dengan naskah akademiknya.
Selain itu, sejumlah regulasi lain yang berpihak pada OAP juga telah kami dorong, dibahas, bahkan disetujui di tingkat paripurna. Namun, sayangnya, pelaksanaannya masih berjalan di tempat.
Secara prosedural, penyusunan dan pembahasan Raperdasus KKR telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam Sidang Paripurna DPR Papua pada Agustus 2019, disepakati bahwa draft Raperdasus tersebut perlu diajukan ke pemerintah pusat sebagai bahan kajian dalam penyusunan Keputusan Presiden (Keppres). Pemerintah daerah Papua kemudian meminta Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk melakukan kajian lanjutan. Hingga kini, nasib draft tersebut masih menggantung—menjadi dokumen yang hidup segan mati tak mau di tumpukan meja birokrasi.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) “Meninjau Ulang Kebijakan Papua: Antara Janji Damai dan Pembangunan Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN di Jayapura pada 29–30 Juli 2025, saya kembali menegaskan sikap yang sama. Pemerintah pusat harus membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta Pengadilan HAM di Tanah Papua. Langkah ini adalah jawaban konkret terhadap dua dari empat akar masalah Papua yang telah dirumuskan LIPI.
Kita berharap, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (PRAGIB) menjadikan hal ini prioritas nasional: membentuk KKR dan Pengadilan HAM sesuai amanat UU Otsus, sekaligus melaksanakan pembangunan tanpa kekerasan.
Sebab, pembangunan tidak akan pernah efektif di tengah konflik. Pemerintah daerah tidak mungkin bekerja maksimal jika di bawah bayang-bayang kekerasan dan ketidakpercayaan. Ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat bahwa damai bukanlah hadiah, tetapi hasil dari keadilan yang ditegakkan.
Pemerintah daerah dan DPR Papua Tengah juga harus serius melaksanakan pembangunan yang berpihak pada rakyatnya sendiri. Regulasi daerah mesti disusun dengan semangat perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap Orang Asli Papua, disertai anggaran yang jelas dan terukur bagi program-program yang langsung menyentuh masyarakat di kampung-kampung baik di balik gunung maupun di pesisir-pesisir jauh yang selama ini belum tersentuh oleh pelayanan publik.
Papua tidak butuh janji, tetapi bukti. Dan bukti itu hanya akan lahir jika negara berani membuka kebenaran, mengakui luka, dan menegakkan keadilan.