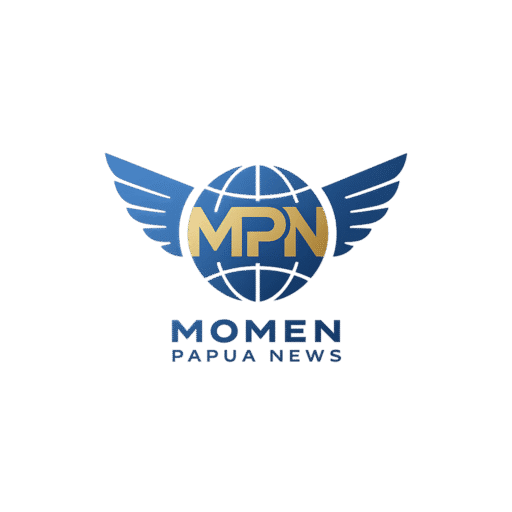PAPUA Tengah sedang terjerembab dalam paradoks pembangunan. Di atas tanah yang menyimpan emas dan tembaga raksasa, justru kemiskinan statistik tumbuh subur. Di ruang sidang, di kantor-kantor pusat, dan di laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), nama Papua Tengah muncul sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Indonesia tahun 2025; minus 9,83 persen pada triwulan kedua, setelah sebelumnya anjlok hingga minus 25,53 persen di awal tahun. Sebuah ironi yang mengguncang logika, di wilayah dengan tambang terbesar di dunia, ekonomi rakyat justru menyusut paling dalam.
Dalam drama ekonomi ini, aktor utamanya jelas Pemerintah pusat, Freeport Indonesia, dan pemerintah daerah Papua Tengah. Ketiganya memegang kunci dalam struktur ekonomi yang timpang. Ketika Freeport tersendat, Papua Tengah ambruk. Lebih dari 70 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Tengah bersumber dari sektor pertambangan. Itu artinya, nasib ekonomi jutaan orang di Mimika, Nabire, hingga Dogiyai bergantung pada satu urat nadi, bijih logam yang keluar dari perut bumi Tembagapura.
Namun pada awal 2025, urat nadi itu tersumbat. Izin ekspor konsentrat Freeport dicabut sementara oleh pemerintah pusat, proyek smelter Gresik terbakar dan belum siap beroperasi, dan produksi tambang pun melambat drastis. Dalam hitungan bulan, mesin utama Papua Tengah berhenti berdetak.
Krisis ini bukan muncul tiba-tiba. Akar-akar perlambatan sudah terlihat sejak 2024. Di tahun itu, ekonomi Papua Tengah tumbuh positif sekitar 4,3 persen, namun pertumbuhannya semu ditopang oleh aktivitas tambang besar, bukan oleh sektor rakyat. Ketika memasuki 2025, efek domino mulai terasa, produksi tambang turun, ekspor terhenti, dan pendapatan daerah menyusut.
BPS mencatat bahwa di semester pertama 2025, ekonomi Papua Tengah sudah terkontraksi 17,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tidak ada provinsi lain di Indonesia yang jatuh sedalam ini.
Titik lemahnya terletak di struktur ekonomi yang rapuh dan tidak beragam. Di luar tambang, sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan konstruksi memang tumbuh, tetapi kontribusinya hanya sekitar 27 persen terhadap PDRB. Artinya, kenaikan di sektor rakyat tidak mampu menambal penurunan tajam di sektor tambang.
Lebih jauh lagi, infrastruktur Papua Tengah masih jauh tertinggal. Jalan antar kabupaten belum terhubung sempurna, energi masih terbatas, dan konektivitas digital belum menjangkau banyak distrik. Di level pemerintahan, provinsi baru ini juga belum sepenuhnya memiliki gedung dan fasilitas birokrasi yang permanen. Akibatnya, penyerapan anggaran lambat dan belanja publik rendah. Pemerintah daerah, dalam banyak hal, masih berjalan di atas tanah yang belum dipadatkan.
Jawaban paling sederhana, karena Papua Tengah dibangun di atas satu kaki ekonomi kaki tambang. Selama ini, tidak ada strategi serius untuk menyeimbangkan struktur ekonominya. Ketika tambang terganggu, seluruh tubuh ekonomi ikut tumbang.
Selain itu, ketergantungan fiskal terhadap pusat terlalu tinggi. Lebih dari 85 persen pendapatan Papua Tengah masih bersumber dari transfer APBN. Sementara PAD provinsi ini sangat kecil hanya sekitar 10 persen dari total pendapatan. Ketika penyaluran dana pusat terlambat atau terganggu oleh administrasi, kegiatan ekonomi daerah langsung terhenti.
Kelemahan lainnya adalah minimnya perencanaan pembangunan jangka menengah yang jelas. Papua Tengah masih beradaptasi sebagai Daerah Otonom Baru, sementara koordinasi antara kabupaten-kabupaten di dalamnya belum solid. Akibatnya, setiap kebijakan berjalan sendiri-sendiri tanpa visi ekonomi yang terpadu.
Papua Tengah tidak akan bisa bangkit hanya dengan menunggu tambang kembali menggeliat. Provinsi ini harus berani membangun poros ekonomi baru yang berpijak pada potensi rakyat dan kemandirian lokal.
Pertama, pemerintah perlu mengembangkan sektor perikanan, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai empat tulang punggung baru sebagaimana direkomendasikan Bank Indonesia. Dari laut Teluk Cenderawasih hingga dataran tinggi nabire, potensi pangan dan laut harus dikelola oleh nelayan dan petani lokal dengan dukungan infrastruktur dingin, transportasi, dan koperasi modern.
Kedua, percepatan infrastruktur dasar menjadi keharusan. Jalan, pelabuhan, listrik, dan internet adalah urat nadi ekonomi rakyat. Pemerintah pusat sudah menaikkan anggaran DOB Papua hingga Rp1,2 triliun pada 2025 dan berencana menjadi Rp3,5 triliun di 2028. Uang ini harus diarahkan untuk membuka konektivitas antarwilayah, bukan terserap habis di biaya birokrasi.
Ketiga, perlu reformasi tata kelola fiskal dan birokrasi daerah. Penyerapan anggaran mesti cepat, transparan, dan berpihak pada proyek produktif. Pemerintah daerah harus didampingi agar mampu merencanakan program ekonomi yang terukur, bukan sekadar menjalankan rutinitas administrasi.
Keempat, Papua Tengah perlu melihat masa depan di sektor hijau. Dengan tutupan hutan luas dan potensi perdagangan karbon, provinsi ini bisa memimpin arah baru ekonomi berkelanjutan—green economy yang bukan hanya menjaga alam, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat adat di rana internasional.
Ekonomi Papua Tengah yang jatuh bukan semata akibat tambang yang berhenti, tetapi karena Pemerintah Provinsi terlalu lama memusatkan pembangunan pada satu poros industri besar dan mengabaikan rakyat di sekelilingnya. Ketika mesin besar berhenti, kita baru sadar bahwa tanah subur di lembah, laut kaya di pantai, dan tenaga kerja lokal di kampung-kampung belum diberi ruang tumbuh.
Papua Tengah seharusnya tidak menjadi catatan kaki dalam statistik nasional, tetapi menjadi cermin, bahwa pembangunan yang adil tidak bisa hanya bertumpu pada emas di perut bumi, tetapi harus tumbuh dari tangan manusia di atasnya.