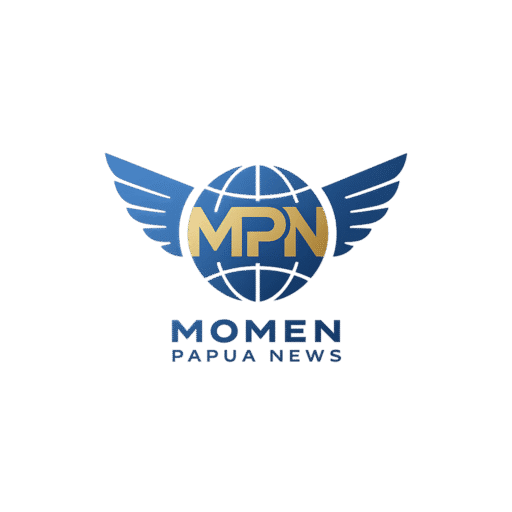Oleh: Jake Merril Ibo
MARAKNYA kasus perundungan (bullying) di sekolah, menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan Indonesia secara khusus di Papua. Fenomena ini bukan lagi sekadar “kenakalan remaja”, tetapi cerminan krisis nilai kemanusiaan dan empati di lingkungan belajar. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan kasus kekerasan di sekolah, baik antar-siswa maupun antara guru dan siswa.
Kekerasan verbal, fisik, maupun digital (cyberbullying) telah menimbulkan luka psikologis yang mendalam bagi korban, menurunkan motivasi belajar, serta mengikis rasa aman di sekolah. Di tengah situasi tersebut, PBM-GKI (Pusat Bantuan Mediasi GKI) menyerukan perlunya inovasi dalam penanganan perundungan — bukan sekadar hukuman, tetapi pemulihan relasi merajut kohesi sosial di lingkungan belajar dan pendidikan damai. Salah satu pendekatan yang relevan dan terbukti efektif di banyak negara adalah program Peer Mediation atau Mediator Sebaya.
Peer Mediation Harus Bisa Jadi Solusi Restoratif di Lingkungan Pendidikan
Peer Mediation adalah pendekatan resolusi dan transformasi konflik, dimana siswa dilatih menjadi mediator bagi teman sebayanya untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, tanpa kekerasan, dan tanpa harus melalui sanksi formal. Pendekatan ini berakar pada prinsip keadilan restoratif (restorative justice), yang menekankan pemulihan hubungan dan tanggung jawab sosial, bukan penghukuman semata.
Di banyak negara seperti Australia, Kanada, dan Finlandia, program peer mediation terbukti mengurangi insiden kekerasan di sekolah hingga 30–50%. Lebih jauh, pendekatan ini meningkatkan empati, keterampilan komunikasi, dan kepemimpinan sosial di kalangan siswa. Dalam konteks Indonesia — yang menempatkan profil pelajar Pancasila sebagai arah pendidikan nasional — peer mediation sejalan dengan nilai gotong royong, empati, dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Tantangan Implementasinya di Indonesia
Namun, penerapan program ini tidak tanpa hambatan. Ada tiga tantangan utama yang perlu dicermati:
a. Budaya sekolah yang masih hierarkis. Sekolah di Indonesia umumnya masih berorientasi pada pendekatan top-down, di mana guru menjadi satu-satunya otoritas moral dan sosial. Dalam sistem seperti ini, ruang partisipasi siswa dalam penyelesaian konflik masih sangat terbatas bahkan memang sama sekali tidak ada.
b. Kurangnya kapasitas guru di sekolah sebagai mediator. Banyak tenaga pendidik belum mendapatkan pelatihan dalam pendekatan mediasi, hal ini menjadi kesulitan tersendiri, karena komunikasi empatik, dan pendidikan damai, belum diterapkan sebagai sebuah value di lingkungan sekolah. Akibatnya, respon terhadap perundungan cenderung reaktif dan hukuman bersifat administrative, bahkan kadang-kadang di sekolah muncul indikasi perundungan, diabaikan saja.
c. Ketiadaan kebijakan institusional yang jelas. Meskipun Permendikbud No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan telah mengatur langkah-langkah preventif, belum ada panduan operasional tentang mekanisme peer mediation sebagai bagian dari sistem resolusi konflik di sekolah.
Arah Kebijakan Harus Menuju Ekosistem Sekolah Damai dan Inklusif
Meskipun program Sekolah Ramah Anak telah diadopsi secara luas di berbagai satuan pendidikan, implementasinya masih bersifat seremonial dan belum menyentuh akar masalah kekerasan di sekolah. Belum ada strategi solutif dan sistematis untuk menciptakan sekolah yang benar-benar bebas dari perundungan.
Untuk membangun ekosistem sekolah yang damai dan inklusif, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang konkret dan berlapis. PBM-GKI mengusulkan beberapa strategi berikut:
1. Integrasi Peer Mediation ke dalam Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Program peer mediation dapat dimasukkan dalam Rencana Aksi Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
2. Pelatihan Mediator Sebaya. Dinas Pendidikan dapat bekerja sama dengan lembaga mediasi profesional (termasuk PBM-GKI) untuk melatih siswa terpilih menjadi peer mediator, dilengkapi modul etika, empati, dan keterampilan komunikasi non-kekerasan.
3. Pembentukan Unit Mediasi Sekolah. Setiap sekolah dapat memiliki School Mediation Unit yang beranggotakan guru wali kelas, guru Bimbingan Konseling, Guru Agama, Guru Pendidikan Pancasila, dan perwakilan siswa. Unit ini menjadi tempat penyelesaian konflik sosial secara restoratif, dan bersifat preventif, mencegah kasus di lingkungan satuan pendidikan sehingga mampu memitigasi kasus perundingan.
4. Pendampingan dan Monitoring Berkelanjutan. Implementasi program peer mediation perlu disertai evaluasi dampak — misalnya melalui survei rasa aman siswa, indeks kekerasan sekolah, dan tingkat keterlibatan siswa dalam kegiatan resolusi konflik.
5. Keterlibatan Orang Tua dan Komunitas. Sekolah perlu melibatkan orang tua dan komunitas lokal melalui forum dialog, pelatihan, dan sosialisasi nilai-nilai anti-kekerasan, agar upaya mediasi sebaya mendapat dukungan sosial yang kuat.
Peran Strategis PBM-GKI dan Kolaborasi Lintas Lembaga
Sebagai lembaga yang berpengalaman dalam bidang resolusi konflik dan keadilan restoratif, PBM-GKI memiliki posisi strategis untuk menjadi mitra pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. PBM-GKI dapat: Mengembangkan modul pelatihan peer mediation yang kontekstual dengan nilai-nilai lokal dan spiritualitas damai; Melatih guru dan siswa menjadi mediator yang mampu memfasilitasi resolusi konflik di sekolah; Melakukan riset kebijakan dan pendampingan evaluatif terhadap pelaksanaan peer mediation di sekolah-sekolah mitra.
Dengan pendekatan berbasis nilai dan kemanusiaan, PBM-GKI dapat berkontribusi menciptakan transformasi budaya sekolah — dari ruang kompetisi menuju ruang kolaborasi.
Harus Terjadi Transformasi Kebijakan Pendidikan
Bullying di sekolah adalah tanda bahwa, pendidikan kita masih berutang pada nilai kemanusiaan. Menindak pelaku memang perlu, tetapi membangun ekosistem damai jauh lebih penting.
Bullying juga bukan sekadar pelanggaran disiplin, tetapi kegagalan sistem pendidikan dalam menumbuhkan empati dan rasa aman. Karena itu, solusi tidak cukup hanya berupa sanksi atau himbauan moral, tetapi perlu perubahan sistemik menuju ekosistem pendidikan yang damai.
Melalui peer mediation, siswa tidak hanya menjadi penerima pendidikan, tetapi juga penggerak perubahan sosial sejak dini.
Sekolah menjadi tempat tumbuhnya generasi yang bukan hanya cerdas, tapi juga berbelas kasih dan bertanggung jawab.
Inilah saatnya kebijakan pendidikan kita bertransformasi — dari sistem yang hanya banyak rapat dan sosialisasi, menuju sistem yang memberdayakan guru dan siswa menjadi duta damai di Tingkat satuan Pendidikan.
Melalui peer mediation, sekolah dapat menjadi ruang pembelajaran hidup — tempat siswa belajar berdialog, memahami perbedaan, dan memulihkan relasi yang rusak. Inilah makna sejati pendidikan: membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga berjiwa adil, empatik, dan damai
(Penulis, adalah Direktur PBM GKI (Pusat Bantuan Mediasi GKI) yang juga fokus pada pengembangan mediasi dan pendidikan damai di lingkungan sekolah. Tinggal di Timika)