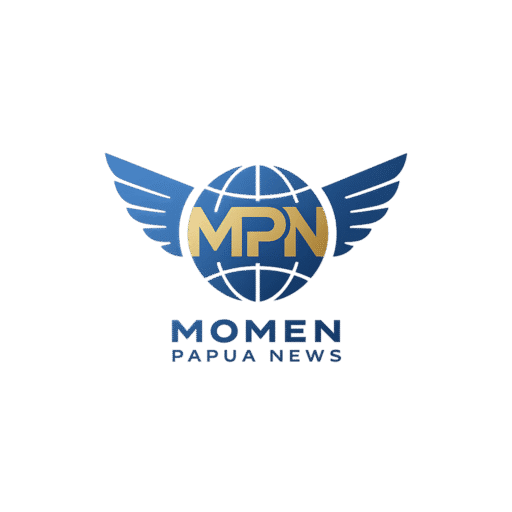Oleh: Jake Merril Ibo (Direktur Pusat Bantuan Mediasi GKI)
Kekuasaan Sebagai Cermin Identitas
Di Tanah Papua, kekuasaan tidak lagi sekadar dimaknai sebagai jabatan formal dalam sistem politik atau birokrasi. Ia telah bertransformasi menjadi penanda identitas, simbol status sosial, bahkan ukuran harga diri. Dalam lanskap sosial yang masih menyimpan luka sejarah, ketimpangan ekonomi, dan kompleksitas politik, kekuasaan sering dipandang sebagai puncak legitimasi dan pengakuan diri.
Kondisi ini melahirkan bukan hanya kompetisi untuk merebut posisi, tetapi juga pola perilaku tertentu di kalangan elit Papua, sebuah kecenderungan yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai “sindrom pick me.” Istilah ini berasal dari budaya populer dan menggambarkan individu yang berusaha keras agar diterima atau dianggap layak oleh pihak yang memiliki dominasi lebih besar, entah itu institusi, kelompok, maupun figur otoritas.
Dalam konteks politik Papua, fenomena tersebut tampak ketika sebagian elit lokal berlomba menunjukkan loyalitas dan kesetiaan kepada pusat kekuasaan di luar komunitasnya sendiri. Upaya mencari legitimasi itu kerap dilakukan dengan mengorbankan kepentingan kolektif masyarakat Papua, sehingga hubungan antara rakyat dan elit menjadi semakin renggang dan penuh kecurigaan.
1. Dari Politik Identitas ke Politik Validasi
Sejarah Papua senantiasa diwarnai oleh ketegangan antara identitas dan kekuasaan. Sejak proses integrasi dengan Indonesia pada dekade 1960-an, dinamika politik di wilayah ini bergerak dalam dua arus utama. Pertama, politik resistensi, yang berfokus pada perjuangan untuk memperoleh pengakuan atas sejarah dan martabat Orang Asli Papua (OAP). Kedua, politik akomodasi, yang ditempuh oleh sebagian elit lokal melalui strategi pragmatis, berpartisipasi dalam sistem kekuasaan nasional guna memperoleh posisi dan akses terhadap sumber daya.
Namun, di tengah dua arus besar tersebut, kini muncul pola baru yang dapat disebut sebagai politik validasi: sebuah orientasi di mana sebagian elit tidak lagi memperjuangkan kepentingan kolektif masyarakatnya, melainkan mencari legitimasi pribadi dari pusat kekuasaan. Mereka tidak lagi berbicara kepada rakyat Papua, tetapi kepada Jakarta, mengincar perhatian dan pengakuan dari struktur kekuasaan nasional.
Dalam konteks ini, kekuasaan berubah menjadi panggung pertunjukan. Para elit tampil bukan sebagai representasi rakyat, melainkan sebagai aktor yang berlomba mendapat tepuk tangan dari penonton yang lebih berpengaruh: pemerintah pusat, partai politik besar, atau korporasi asing. Fenomena ini menandai hadirnya bentuk baru dari kolonisasi mental, bukan melalui kekuatan militer, melainkan melalui godaan legitimasi, penghargaan, proyek, dan jabatan.
2: Sindrom “Pick Me”, Pola Lama dalam Wajah Baru
- Asal-usul Istilah
Istilah pick me awalnya dikenal luas di ranah media sosial, digunakan untuk menggambarkan seseorang yang berupaya berlebihan menyesuaikan diri demi diterima atau disukai oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar.
Dalam konteks elit Papua, gejala ini tampak ketika sejumlah figur publik merasa harus menegaskan loyalitas tanpa syarat kepada kekuasaan pusat agar dipandang “layak dipercaya” dan mendapatkan legitimasi politik.
Fenomena tersebut tercermin dalam berbagai praktik keseharian politik, antara lain:
- Pernyataan publik yang menyanjung kebijakan pemerintah pusat, meski kebijakan tersebut justru berpotensi merugikan masyarakat Papua.
- Pertunjukan kedekatan simbolik dengan pejabat nasional melalui media, sebagai upaya memperkuat citra loyalitas.
- Penciptaan narasi “Papua aman dan kondusif”, yang sering kali lebih ditujukan untuk menjaga kesan stabilitas di mata pusat daripada menggambarkan realitas di lapangan.
- Pemanfaatan proyek pembangunan sebagai instrumen negosiasi politik, bukan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks ini, sindrom pick me di kalangan elit Papua tidak hanya mencerminkan strategi politik, tetapi juga krisis representasi, ketika kebutuhan akan pengakuan dari kekuasaan menggantikan tanggung jawab moral terhadap rakyatnya sendiri.
- Ketika Elit Jadi Agen Legitimasi
Sindrom pick me pada akhirnya mendorong sebagian elit Papua untuk, sering kali tanpa disadari, menjadi perpanjangan tangan legitimasi kekuasaan dari luar. Mereka tampil sebagai “wajah Papua” di ruang publik nasional, sosok-sosok yang dimunculkan untuk memberi kesan bahwa “semua berjalan baik”, meskipun realitas di akar rumput justru menunjukkan sebaliknya: masyarakat masih bergulat dengan kemiskinan, ketimpangan, dan kekerasan struktural yang terus berlangsung.
Fenomena semacam ini sejatinya bukan hal baru. Sejak diberlakukannya Otonomi Khusus (Otsus) jilid pertama, banyak tokoh lokal memperoleh ruang politik yang luas, dari jabatan gubernur, bupati, anggota DPRP dan DPRK, hingga keanggotaan di Majelis Rakyat Papua (MRP). Namun, peluang tersebut tidak selalu digunakan untuk memperkuat posisi rakyat. Sebagian elit justru memanfaatkan ruang itu untuk mengukuhkan kepentingan pribadi, menjadikan politik sebagai arena akumulasi kekuasaan dan kekayaan.
Proyek-proyek infrastruktur berubah menjadi sarana patronase politik; dana Otsus mengalir tanpa dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, sementara suara-suara kritis kerap dibungkam atas nama stabilitas dan harmoni. Dalam situasi semacam ini, kekuasaan tidak lagi menjadi alat emansipasi, melainkan cermin dari ketergantungan baru, di mana pengakuan dari luar lebih diutamakan daripada keadilan bagi sesama di dalam.
3. Politik Simbol dan Panggung Kekuasaan
- Kekuasaan sebagai Pertunjukan
Dalam lanskap politik Papua masa kini, kekuasaan kerap menyerupai panggung teater. Ada panggung yang megah, penonton yang menilai, dan peran-peran yang harus dimainkan dengan penuh kepatuhan. Para elit pun belajar untuk menyesuaikan diri dengan naskah yang ditulis oleh kekuatan yang lebih besar, memainkan peran sesuai tuntutan sutradara politik dari luar diri dan komunitasnya.
Ketika seorang pejabat Papua berdiri di depan kamera, mengenakan noken di bahu dan mahkota bulu di kepala, sambil berbicara tentang pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan, sering kali itu bukan sekadar pidato, melainkan tampilan simbolik dari narasi resmi: citra Papua yang damai, aman, dan sepenuhnya sejalan dengan visi nasional.
Namun di balik segala ornamen dan kostum adat yang megah itu, roh perjuangan banyak yang perlahan memudar. Yang tersisa adalah peran-peran kosong yang diulang dari satu panggung ke panggung berikutnya, sebuah drama politik tanpa kendali, di mana para aktor lokal tampil meyakinkan, tetapi naskah dan arah cerita tetap ditulis oleh pihak lain.
- Estetika Kekuasaan dan Kekosongan Makna
Simbol-simbol budaya Papua kini semakin sering dijadikan hiasan kekuasaan, bukan sumber nilai yang menuntun arah kebijakan. Ornamen etnik menghiasi dinding kantor pemerintahan, namun keputusan-keputusan yang lahir di dalamnya kerap tidak berpihak pada semangat asli “melindungi tanah dan manusia Papua.” Upacara adat dijadikan latar seremoni pelantikan pejabat, tetapi makna luhur adat tentang kejujuran, keseimbangan, dan tanggung jawab moral justru tersisih dari praktik kekuasaan itu sendiri.
Dalam ruang politik yang seperti ini, sindrom pick me menemukan tanah yang subur untuk tumbuh. Ketika simbol menjadi lebih penting daripada substansi, identitas berubah menjadi sekadar atribut visual tanpa kedalaman makna. Para elit berlomba menampilkan “Papua-ness” di hadapan public, dengan busana, bahasa, atau gestur adat, namun pada saat yang sama, koneksi spiritual dan etis dengan akar budaya yang seharusnya menjadi sumber kekuatan mereka perlahan menghilang.
4. Psikologi Kekuasaan dan Trauma Kolonial
Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari jejak panjang trauma kolonialisme yang membentuk kesadaran sosial orang Papua. Selama berabad-abad, masyarakat Papua ditempatkan sebagai objek dalam relasi kuasa, mulai dari misi keagamaan yang membawa “peradaban”, perusahaan tambang yang mengeksploitasi sumber daya alam, hingga struktur birokrasi negara yang memusatkan kendali. Pengalaman panjang sebagai “yang dikuasai” melahirkan pola psikologis tertentu: keinginan untuk diterima oleh pihak yang dominan, karena penerimaan tersebut dipersepsikan sebagai tanda keberhasilan dan pengakuan sosial.
Bagi sebagian elit Papua yang berhasil menembus lingkar kekuasaan nasional, keberhasilan itu sering dimaknai sebagai kemenangan besar, simbol bahwa mereka akhirnya diakui. Namun, kemenangan semacam itu kerap bersifat seremonial, lebih merupakan kesempatan untuk duduk di meja para penguasa ketimbang kemampuan untuk mengubah nasib rakyatnya sendiri. Mereka mungkin memperoleh pengakuan, tetapi keberpihakan terhadap masyarakatnya perlahan memudar.
Dalam kajian psikologi sosial, gejala ini dikenal sebagai internalisasi penindasan, suatu kondisi di mana korban mulai mengadopsi cara pandang dan nilai-nilai pihak yang menindasnya, menjadikan standar kekuasaan eksternal sebagai ukuran diri.
Dalam konteks Papua, sindrom pick me dapat dibaca sebagai manifestasi psikologis dari luka kolektif yang belum sepenuhnya sembuh, luka yang diwariskan oleh sejarah panjang ketimpangan dan relasi kuasa yang timpang antara “pusat” dan “pinggiran.”
5. Ekonomi Politik dari Sindrom “Pick Me”
- Proyek dan Patronase
Di balik gejala ini tersembunyi logika ekonomi-politik yang kuat, yakni mekanisme patronase kekuasaan. Arus dana, proyek, dan jabatan dari pusat ke Papua menciptakan jaringan ketergantungan yang rumit, di mana sebagian elit lokal berperan sebagai perantara politik untuk menjaga apa yang disebut sebagai “stabilitas.” Dalam ekosistem seperti ini, loyalitas menjadi mata uang utama, mereka yang paling pandai menunjukkan kesetiaan biasanya memperoleh bagian terbesar dari aliran kekuasaan tersebut.
Sindrom pick me tumbuh subur di dalam sistem patronase ini. Para elit yang ingin mempertahankan posisi akan berlomba menampilkan kesetiaan simbolik kepada patron mereka di pusat: muncul di media nasional dengan narasi yang sejalan dengan pemerintah, rutin menghadiri acara seremonial di Jakarta, hingga menyerang sesama tokoh Papua yang bersikap kritis, semata untuk membuktikan bahwa mereka bukan bagian dari “masalah.”
Dalam lingkaran semacam itu, kekuasaan tidak lagi menjadi alat pengabdian, melainkan arena transaksi antara kesetiaan dan keberlangsungan posisi.
- Politik Fragmentasi
Kekuasaan di Papua tampak membangun pola yang secara sadar mereproduksi fragmentasi politik. Pemekaran provinsi, pembentukan kabupaten baru, hingga penunjukan pejabat sementara sering dikemas dalam wacana “pemberdayaan daerah”, meski pada kenyataannya langkah-langkah tersebut justru meneguhkan ketergantungan struktural terhadap pusat.
Dalam skema semacam ini, sindrom pick me berfungsi sebagai instrumen seleksi kekuasaan, menentukan siapa yang dianggap layak dan “aman” untuk memimpin wilayah baru. Loyalitas personal terhadap patron politik menjadi ukuran utama dalam proses penentuan jabatan, menggantikan prinsip meritokrasi yang seharusnya menitikberatkan pada kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan publik.
Dengan demikian, politik pemekaran tidak sekadar memperluas batas administratif, melainkan juga menambah simpul-simpul kendali kekuasaan baru. Dalam sistem patronase modern di Tanah Papua, kesetiaan politik berubah menjadi komoditas utama, lebih berharga daripada profesionalisme atau keberpihakan kepada rakyat.
6. Media, Citra, dan Politik Pencitraan
Dalam era digital, gejala ini mengalami percepatan dan perluasan yang signifikan. Para elit Papua kini berlomba membangun citra diri di ruang virtual, menampilkan kedekatan dengan pejabat nasional, mempublikasikan foto pertemuan di istana, atau menyoroti penampilan mereka di forum-forum internasional. Aktivitas semacam itu menjadikan eksposur publik sebagai bukti eksistensi politik, bukan sebagai wujud tanggung jawab atau transparansi terhadap publik.
Media lokal, pada saat yang sama, sering kali terjebak dalam peran sebagai pengeras suara kekuasaan. Alih-alih melakukan pendalaman atas kebijakan atau mengkritisi substansinya, mereka lebih banyak menyiarkan aktivitas seremonial dan simbolik. Akibatnya, politik di Papua tampil di mata masyarakat sebagai panggung parade figur, tempat yang lebih menonjolkan siapa yang tampak “dipilih” ketimbang siapa yang sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat.
Dalam ruang komunikasi yang dikendalikan algoritma, sindrom pick me berubah menjadi bagian dari politik pencitraan digital. Mereka yang paling sering muncul di linimasa dianggap paling berpengaruh, meskipun sering kali justru mereka yang bekerja diam-diam di akar rumput yang membawa perubahan nyata. Dengan demikian, politik di era digital tidak lagi sekadar persoalan gagasan, tetapi juga kompetisi visibilitas, siapa yang paling berhasil mempertahankan dirinya dalam sorotan publik.
7. Resistensi dan Harapan Baru
Tidak semua elit Papua terseret dalam pola patronase dan pencitraan semu ini. Masih ada tokoh-tokoh yang berani melawan arus, mengambil risiko untuk bersuara lantang melawan ketidakadilan dan menolak tunduk pada narasi kekuasaan yang dominan. Mereka kerap dilabeli sebagai provokator atau anti-pembangunan, namun justru merekalah yang menjaga nurani dan moralitas politik Papua, mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa keberpihakan hanyalah kepura-puraan.
Di sisi lain, generasi muda Papua mulai menunjukkan kesadaran baru terhadap bahaya sindrom pick me. Para aktivis, jurnalis, dan akademisi muda menggunakan media independen sebagai ruang perlawanan intelektual, mengkritisi praktik patronase sekaligus menuntut transparansi dan keadilan. Mereka menolak sekadar menjadi penonton di panggung kekuasaan yang penuh sandiwara, dan memilih mendirikan panggung mereka sendiri, berupa forum diskusi, riset kritis, serta karya seni yang jujur menggambarkan realitas kehidupan rakyat Papua.
8. Jalan Keluar — Membangun Etika Kekuasaan Baru
Mengatasi sindrom pick me bukanlah tugas yang sederhana. Fenomena ini telah berakar kuat dalam sistem birokrasi dan budaya politik Papua selama beberapa dekade, menjadikannya bagian dari struktur sosial yang sulit diurai. Meski demikian, ada sejumlah langkah strategis yang dapat ditempuh untuk membangun kesadaran baru dan memulihkan integritas politik di Tanah Papua:
- Rekonstruksi Kesadaran Kolektif
Pendidikan politik perlu diarahkan pada pembentukan kesadaran kritis, bukan sekadar penanaman slogan-slogan pembangunan. Masyarakat Papua harus kembali memahami bahwa kekuasaan sejati tidak bersumber dari “atas”, melainkan tumbuh dari kepercayaan, dukungan, dan partisipasi rakyat sendiri. Dengan cara ini, legitimasi sosial dapat menggantikan ketergantungan pada legitimasi politik formal. - Reformasi Tata Kelola Otonomi Khusus dan Dana Publik
Pengelolaan dana Otsus serta berbagai proyek pembangunan mesti dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Transparansi anggaran bukan hanya soal laporan keuangan, tetapi juga mekanisme pengawasan publik yang memungkinkan masyarakat menilai sejauh mana kebijakan dijalankan sesuai kebutuhan mereka. Keterlibatan masyarakat harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, bukan sekadar formalitas administratif. - Revitalisasi Nilai-Nilai Adat Papua
Prinsip-prinsip adat seperti keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan yang selama ini menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat Papua perlu dihidupkan kembali dalam praktik politik modern. Kekuasaan tidak boleh dipahami sebagai alat dominasi, melainkan sebagai amanah sosial untuk melindungi tanah, manusia, dan masa depan generasi berikutnya. Revitalisasi nilai-nilai adat dapat menjadi basis moral dalam menghadapi politik transaksional. - Penguatan Media Independen dan Literasi Publik
Media lokal harus kembali pada fungsi utamanya sebagai ruang kontrol sosial dan penyampai suara rakyat, bukan sekadar corong pencitraan elit. Untuk itu, perlu dikembangkan pendidikan literasi media yang memungkinkan masyarakat mengenali manipulasi informasi dan simbol kekuasaan palsu. Media yang kritis dan independen dapat menjadi benteng terakhir melawan dominasi narasi tunggal dari pusat kekuasaan.
9. Kekuasaan Sebagai Ruang Pemulihan
Bayangkan apabila kekuasaan di Tanah Papua tidak lagi dijalankan untuk mempertontonkan kesetiaan, melainkan digunakan sebagai ruang penyembuhan bagi luka-luka kolektif yang diwariskan sejarah. Dalam tatanan seperti itu, para pemimpin yang lahir dari rahim rakyat akan memandang jabatan bukan sebagai panggung pertunjukan, tetapi sebagai amanah etis dan tanggung jawab moral. Mereka tidak perlu mencari legitimasi dari pusat kekuasaan, sebab legitimasi sejati telah mereka dapatkan dari kepercayaan dan kasih rakyatnya sendiri.
Kekuasaan yang menyembuhkan adalah kekuasaan yang mau mendengar, ia tidak haus akan tepuk tangan, tidak membutuhkan sorotan kamera. Tujuannya bukan pengakuan, melainkan perubahan yang nyata. Sebab di saat kekuasaan mampu mendengarkan dengan tulus, di sanalah damai Papua bukan lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang tumbuh dari hati rakyatnya sendiri.
Dari Panggung ke Pelayanan
Sindrom pick me di kalangan elit Papua mencerminkan krisis identitas politik, ketika kekuasaan tidak lagi dimaknai sebagai amanah, melainkan sebagai panggung pertunjukan. Di atas panggung itu, banyak aktor tampil dengan gaya memukau, tetapi kisah yang mereka perankan bukanlah cerita rakyat Papua.
Kini sudah waktunya tirai pertunjukan semu itu diturunkan, dan panggung politik dikembalikan kepada keaslian maknanya. Politik yang sejati bukan tentang siapa yang paling disenangi penguasa, melainkan siapa yang paling tulus mencintai rakyatnya.
Papua tidak membutuhkan lebih banyak aktor yang pandai memainkan peran, melainkan pelayan yang berani mengabdi dalam senyap. Bukan mereka yang berteriak “pilih saya,” tetapi mereka yang dalam hatinya berbisik, “saya memilih Papua.”