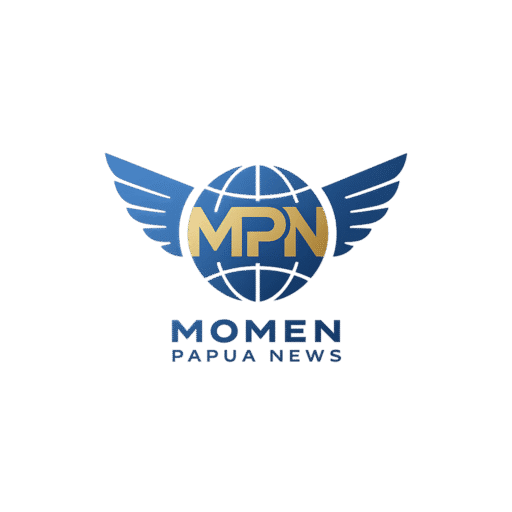Oleh: Jake Merril Ibo
Pendahuluan: Ketika Suara yang Kecil Tenggelam di Tengah Suara yang Lebih Nyaring
Di Tanah Papua, kata “keadilan” sering terdengar seperti gema jauh di perbukitan, lantang dalam teks, namun samar dalam kenyataan. Banyak orang, terutama mereka yang hidup di lapisan sosial paling rentan, tahu betul bahwa jarak antara hukum dan keadilan bukan sekadar retakan, tetapi jurang. Jurang yang dalam, gelap, dan sering kali sulit dijembatani.
Dalam kenyataan sehari-hari, ketika seseorang dipukul, dirampas haknya, atau diperhadapkan dengan kekerasan, respons masyarakat lazim berbunyi, “Laporkan ke polisi.” Di balik kalimat sederhana itu tersimpan keyakinan bahwa hukum formal adalah satu-satunya sumber kebenaran. Bahwa hukum tertulis adalah ukuran absolut dari apa itu keadilan.
Namun realitas di Papua bergerak dengan logika lain. Banyak masyarakat kecil yang masuk ke kantor polisi bukan menemukan keadilan, tetapi hambatan baru: birokrasi yang berbelit, laporan yang menghilang, berkas yang tidak lengkap, BAP yang tidak mencantumkan pelaku, atau sikap aparat yang dingin dan jauh dari empati.
Di sinilah kita melihat bagaimana narasi dominan, bahwa keadilan hanya ada pada hukum formal telah menggeser, bahkan menenggelamkan, suara-suara lemah yang seharusnya dilindungi.
Narasi Dominan: Keadilan yang Disempitkan dalam Kaca Mata Formal
Narasi dominan adalah cerita besar yang diterima begitu saja oleh masyarakat dan institusi. Di Papua, narasi dominan tentang keadilan dapat dirangkum dalam satu kalimat:
“Keadilan = Prosedur Hukum.”
Padahal kenyataannya, mengikuti prosedur tidak selalu berujung pada keadilan. Prosedur hanyalah mekanisme; bukan moralitas. Tetapi sistem saat ini menjadikan prosedur sebagai parameter tunggal, sehingga pengalaman hidup korban kerap dikesampingkan.
Ketika seorang anak muda Papua dipukul, wajahnya rusak, kepalanya memar, dan ia datang melapor, sistem sering kali menilai kasus tersebut bukan dari luka yang ia alami, tetapi dari lengkap atau tidaknya dokumen.
Ketika laporan hilang, atau ketika pelaku tidak dimasukkan dalam BAP, narasi dominan kembali diucapkan:
“Ini sudah sesuai prosedur.”
Padahal masyarakat tidak peduli soal prosedur, mereka peduli soal kebenaran, perlindungan, dan pemulihan. Mereka peduli agar luka itu tidak terulang. Mereka peduli agar pelaku tidak bebas berkeliaran. Mereka peduli agar hidup mereka bernilai di mata negara.
Namun narasi dominan memaksa mereka percaya bahwa keadilan hanya bisa lahir dari jalur formal, sehingga pengalaman emosional, trauma, dan ketakutan mereka menjadi tidak dianggap sebagai bagian dari kebenaran. Narasi dominan ini pada dasarnya mereduksi keadilan menjadi administrasi, bukan kemanusiaan.
Kebenaran Tunggal: Ketika Negara Memonopoli Definisi Keadilan
Dalam banyak kasus di Papua, negara melalui aparat dan institusi formal sering menjadi satu-satunya pihak yang dianggap berhak mendefinisikan apa itu kebenaran, apa itu kesalahan, apa itu keadilan, dan siapa yang benar serta siapa yang salah.
Inilah yang disebut sebagai kebenaran tunggal. Sebuah konsep yang dikritik oleh teori postmodern. Kebenaran tunggal meniadakan keragaman perspektif, menolak pengalaman korban, dan meredam suara mereka yang lemah. Ia memposisikan institusi formal sebagai satu-satunya otoritas untuk menentukan makna peristiwa.
Di Papua, kebenaran tunggal bekerja melalui dokumen resmi, BAP, laporan polisi, penilaian penyidik, interpretasi aparat, dan hierarki kekuasaan.
Ketika seorang ibu Papua menangis karena anaknya dipukul, itu dianggap “klaim emosional” yang harus dibuktikan dengan prosedur. Ketika keluarga korban meminta perbaikan BAP karena pelaku tidak dicantumkan, jawaban aparat adalah, “Tidak bisa. Laporannya sudah masuk ke pusat.”
Pernyataan itu bukan hanya alasan birokratis, itu adalah pengukuhan kebenaran tunggal. Sebuah cara halus untuk mengatakan bahwa kebenaran versi korban tidak valid, sementara versi formal: tidak lengkap, tidak akurat, dan mengabaikan pelaku, tetap diakui sebagai satu-satunya kebenaran sah.
Postmodernisme dan Runtuhnya Kebenaran Tunggal
Dalam teori Postmodern, kita diajak menyadari bahwa Kebenaran itu jamak. Keadilan itu cair. Narasi manusia itu kompleks. Setiap konflik mengandung banyak versi cerita. Tidak ada institusi yang boleh mengklaim monopoli atas realitas.
Postmodernisme bukan sekadar kritik filosofis; ia menawarkan jalan praktis, terutama dalam konflik sosial di Papua. Dengan mematahkan anggapan bahwa hanya hukum formal yang menentukan keadilan, postmodernisme membuka ruang bagi narasi korban, pengalaman masyarakat, penyelesaian berbasis komunitas, mekanisme adat, dialog keluarga, dan mediasi humanis yang berfokus pada pemulihan.
Postmodernisme mengajarkan bahwa keadilan tidak harus dibuktikan dengan dokumen, melainkan dengan pengakuan. Pengakuan bahwa manusia berhak atas rasa aman, martabat, dan suara atas hidupnya sendiri.
Dengan kata lain, postmodernisme memulihkan keadilan dari tangan yang berkuasa (kekuasaan) kembali kepada tangan manusia.
Keadilan yang Tak Pernah Selesai: Proses, Bukan Produk
Salah satu inti gagasan besar postmodern adalah bahwa keadilan bukan sebuah tujuan akhir, melainkan proses yang terus bergerak. Keadilan bukan sesuatu yang diselesaikan dengan satu surat, satu tanda tangan, atau satu putusan hukum. Ia adalah perjalanan panjang yang menuntut: mendengar, melihat, merasakan, memahami, mengoreksi, dan merawat luka sosial.
Ketika negara mengatakan, “Kasus ini sudah selesai, sesuai prosedur,” yang sebenarnya selesai adalah pekerjaan administrasi, bukan keadilan. Sebab keadilan bagi korban mungkin masih menggantung seperti pelaku masih bebas, trauma belum sembuh, hubungan sosial masih retak, ketakutan masih membayangi, luka batin masih mengalir.
Keadilan yang formal sering kali berakhir begitu dokumen ditandatangani. Tetapi keadilan yang manusiawi baru dimulai ketika korban didengar.
Mereka yang Tak Punya Suara: Siapa yang Sebenarnya Dilupakan?
Ada tiga kelompok utama yang sering kehilangan suara dalam konflik di Papua:
- Warga kecil yang tidak percaya sistem. Mereka tidak melapor karena: takut dianggap pembuat masalah, takut pada aparat, tidak paham prosedur, atau sudah terlalu sering kecewa.
- Anak muda Papua yang rentan kriminalisasi. Bagi mereka, keadilan formal sering terasa seperti jebakan. Mereka mudah dicurigai, mudah disalahkan, dan sulit diperlakukan sebagai korban bahkan distigma sebagai pelaku.
- Keluarga korban yang menghadapi birokrasi tanpa pendampingan. Tanpa pendamping hukum, mereka berjalan sendiri dalam labirin administratif yang tidak manusiawi.
Mereka semua hanyalah manusia biasa yang ingin hidup tenang tetapi terperangkap dalam sistem yang tidak memandang mereka sebagai pusat, melainkan sebagai beban.
Apa yang Salah dengan Narasi Hukum Formal?
Kita harus jujur mengakui bahwa masalah bukan pada hukum sebagai konsep, melainkan pada pengoperasian hukum itu sendiri. Di Papua, hukum formal sering gagal karena:
- Tidak sensitif terhadap konteks sosial Papua. Papua punya sejarah panjang luka, trauma, dan ketidakpercayaan terhadap negara.
- Tidak menyediakan ruang bagi korban untuk didengar. Korban dianggap sekadar pelengkap berkas, bukan subjek utama keadilan.
- Tidak mampu menangani kerentanan sosial. Masyarakat kecil rentan terhadap tekanan, intimdasi, dan manipulasi.
- Tidak membuka diri terhadap kebenaran alternatif. Narasi adat, budaya, dan pengalaman hidup dianggap kurang “legal.”
- Sering kali diwarnai ketimpangan kekuasaan. Kekuasaan mengatur arah kasus, bukan kebenaran.
Narasi hukum formal hanya bekerja untuk mereka yang kuat, berpendidikan, punya akses, atau punya uang. Sementara mereka yang tak punya suara tetap tertinggal di luar sistem.
Melampaui Hukum: Membangun Keadilan yang Lebih Manusiawi
Untuk Papua, keadilan harus bersifat multidimensional. Ia harus mencakup:
1. Keadilan Formal. Hukum tetap penting, tidak ada yang keliru dengan Mindset keadilan yang Legisme / Dogmatis (peraturan/hukum/putusan), bahkan merupakan syarat terciptanya Keteraturan dan Kepastian hukum, tetapi harus transparan, bersih, dan manusiawi.
2. Keadilan Sosial. Korban perlu didampingi; pelaku perlu dikenali; keluarga perlu dilibatkan. Karena lebih hakiki daripada itu: “Kesalingterhubungan yang harmonis membuka ruang dan waktu untuk kita bahagia.
3. Keadilan Adat. Komunitas Papua punya mekanisme penyelesaian trauma yang lebih cepat dan lebih dalam dari prosedur formal.
4. Keadilan Naratif. Setiap pihak harus diberi ruang bercerita tanpa takut dibungkam atau disalahkan.
5. Keadilan Spiritual. Papua bukan hanya tanah fisik, tetapi tanah yang bernapas dalam keyakinan, relasi, dan doa.
Jika semua dimensi ini bekerja bersama, barulah keadilan bisa terasa di tubuh sosial Papua.
Harapan: Membuka Jalan bagi Suara yang Selama Ini Dibungkam
Papua tidak membutuhkan sistem hukum baru; Papua membutuhkan cara baru membaca hukum. Keadilan harus turun dari menara prosedural dan berjalan kaki menemui masyarakat. Keadilan harus mendengar cerita korban, bukan hanya membaca dokumen. Keadilan harus peka terhadap trauma, bukan hanya kepada bukti formal.
Ketika suara yang kecil mulai berani berbicara, ketika narasi korban tidak lagi ditertawakan, ketika aparat bersedia duduk mendengarkan sebelum menulis laporan, ketika masyarakat percaya bahwa saran mereka tidak akan lenyap di meja kantor polisi, maka di sanalah kita melihat tanda-tanda bahwa narasi dominan mulai runtuh.
“Keadilan bukan milik negara. Keadilan adalah milik manusia. Dan manusia Papua berhak atas keadilan.”
Penutup: Saatnya Narasi Baru untuk Papua
Kita harus berani mengatakan dengan jujur: narasi dominan telah gagal memberi keadilan bagi mereka yang tidak punya suara.
Kini saatnya kita menciptakan narasi baru, narasi yang melihat keadilan sebagai proses panjang yang tidak pernah selesai, narasi yang menghargai banyak perspektif, narasi yang berpihak pada manusia, bukan pada prosedur.
Keadilan bagi Papua harus lahir dari: keberanian moral, ruang dialog, keterbukaan bercerita, penghormatan pada kebenaran jamak, dan kesediaan untuk meruntuhkan kebenaran tunggal.
Karena ketika suara yang kecil didengar, Papua akan menjadi tempat yang lebih adil—bukan karena hukum bekerja, tetapi karena kemanusiaan bekerja.