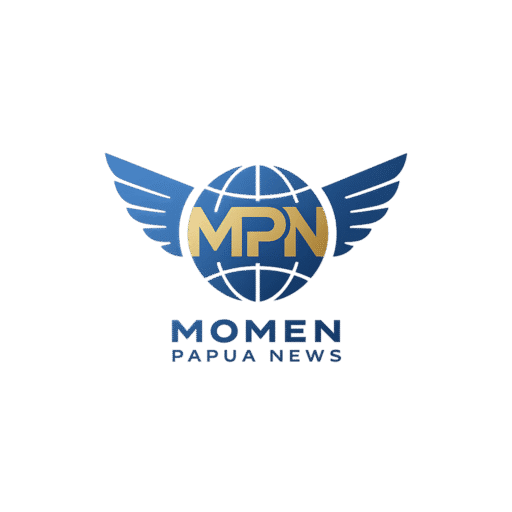Konflik yang Tak Pernah Usai
SELAMA dua dekade terakhir, konflik sosial dan politik di Tanah Papua menunjukkan pola yang berulang: kekerasan terjadi, masyarakat mengalami penderitaan, dan berbagai rekomendasi penyelesaian konflik disampaikan oleh lembaga negara maupun masyarakat sipil. Namun, alih-alih mereda, konflik justru berkembang dalam bentuk yang semakin kompleks, melibatkan berbagai aktor seperti militer, aparat keamanan, kelompok sipil bersenjata, dan komunitas lokal.
Sebagian besar pendekatan penyelesaian konflik yang diimplementasikan masih berpusat pada pendekatan negara (state-centric approach), di mana perdamaian dianggap dapat tercapai melalui intervensi dari atas ke bawah (top-down peacebuilding). Padahal, dinamika kekerasan di lapangan seringkali juga dipicu oleh reaksi masyarakat lokal yang merasa tertindas, tidak diakui, atau kehilangan rasa keadilan.
Fenomena ini mengindikasikan adanya paradoks kepemimpinan moral di tingkat lokal. Baik elit politik, lembaga hak asasi manusia, maupun tokoh adat dan agama sering kali belum menunjukkan keberanian untuk memulai proses penyembuhan sosial dari dalam komunitas sendiri. Pendekatan gereja pun lebih banyak belum memiliki metode yang tepat untuk menyembuhkan luka batin dari umat-Nya. Upaya penyelesaian konflik yang bersifat politis dan reaktif, terutama yang menuntut perubahan dari luar, sering kali mengabaikan dimensi transformasi sosial dan kultural di tingkat akar rumput.
Pengalaman dari berbagai negara pascakonflik menunjukkan bahwa perdamaian berkelanjutan tidak lahir semata-mata dari intervensi militer atau kebijakan pemerintah pusat, melainkan melalui rekonsiliasi batin, pemulihan memori kolektif, dan proses penyembuhan sosial yang dilakukan dari bawah ke atas (bottom-up peacebuilding). Oleh karena itu, penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan baru yang lebih humanis, sehingga mampu menempatkan empati, komunikasi reflektif, dan keterampilan mendengar aktif sebagai fondasi utama dalam membangun kembali kepercayaan sosial dan kohesi antar-komunitas.
Asimetri Narasi dan Tanggung Jawab dalam Konflik Papua
Dalam wacana publik nasional, narasi yang paling dominan mengenai konflik Papua adalah bahwa negara bersikap represif terhadap masyarakat Papua. Narasi ini memiliki dasar faktual yang kuat, mengingat masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum memperoleh penyelesaian hukum maupun keadilan bagi korban. Namun demikian, pendekatan analitis yang terlalu menitikberatkan pada kesalahan negara berpotensi mengabaikan kompleksitas realitas kekerasan di lapangan.
Berbagai laporan menunjukkan bahwa kekerasan di Papua tidak hanya dilakukan oleh aparat negara, tetapi juga oleh sebagian kelompok masyarakat sipil bersenjata. Kekerasan ini kerap menargetkan pendatang, aparat keamanan, maupun sesama warga sipil yang memiliki perbedaan pandangan politik. Fenomena ini menggambarkan bahwa konflik di Papua bersifat multidimensional, melibatkan aktor negara dan non-negara yang sama-sama berkontribusi pada siklus kekerasan yang berkepanjangan.
Sayangnya, aspek ini jarang mendapatkan ruang dalam diskursus publik maupun kebijakan. Banyak lembaga seperti Komnas HAM, DPR Papua, tokoh gereja, maupun organisasi masyarakat sipil cenderung diam atau hanya menyoroti tanggung jawab satu pihak yaitu negara. Akibatnya, tidak muncul kesadaran kolektif di tingkat akar rumput bahwa kekerasan, tanpa memandang pelakunya hanya memperpanjang penderitaan masyarakat Papua sendiri.
Oleh karena itu, perdamaian sejati tidak akan terwujud apabila proses rekonsiliasi hanya menuntut perubahan dari satu pihak, sementara pihak lain terus mempertahankan klaim kebenaran moralnya. Pendekatan yang lebih seimbang, reflektif, dan berbasis empati diperlukan untuk mendorong pengakuan timbal balik dan transformasi sosial yang lebih mendasar di Papua.
Budaya Kekerasan Yang Diwariskan
Konflik yang terjadi di Tanah Papua merepresentasikan bentuk kekerasan struktural yang telah bertransformasi menjadi budaya kekerasan (culture of violence). Sejak masa integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga periode kontemporer, masyarakat Papua hidup dalam ekosistem sosial yang secara perlahan menormalisasi kekerasan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, kekerasan tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan sosial, melainkan sebagai alat komunikasi sosial dan politik untuk menegaskan eksistensi, menuntut keadilan, atau mengekspresikan kekecewaan terhadap otoritas.
Proses historis yang panjang ini melahirkan siklus kekerasan yang saling membalas: tindakan represif aparat negara sering direspon dengan perlawanan bersenjata oleh sebagian kelompok masyarakat, sedangkan pelanggaran hak yang tidak ditangani secara adil memicu tindakan brutal sebagai bentuk ekspresi frustrasi kolektif. Pola ini memperkuat persepsi bahwa kekerasan merupakan satu-satunya cara untuk didengar dan diakui, sehingga menciptakan lingkaran setan kekerasan yang sulit diputus.
Akibatnya, ruang dialog, mediasi, dan komunikasi reflektif menjadi tumpul dan kehilangan legitimasi. Bahasa kekerasan menggantikan bahasa kemanusiaan, dan empati sosial terkikis oleh ketakutan dan dendam yang diwariskan lintas generasi. Dengan demikian, akar konflik Papua tidak semata-mata terletak pada dimensi politik, ekonomi, atau identitas etnis, tetapi juga pada internalisasi kekerasan sebagai logika sosial yang diwariskan secara turun-temurun.
Kegagalan Pendekatan Formal
Selama dua dekade terakhir, pemerintah pusat telah meluncurkan beragam inisiatif untuk meredam konflik dan mempercepat pembangunan di Tanah Papua, antara lain melalui program Otonomi Khusus (Otsus), kebijakan Papua Damai, serta pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai bagian dari strategi pembangunan terintegrasi. Meskipun secara normatif kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat integrasi nasional, dalam praktiknya, pendekatan yang diterapkan cenderung bersifat struktural dan administratif, bukan transformatif.
Fokus kebijakan pemerintah masih berorientasi pada pembangunan fisik, pengelolaan anggaran, dan stabilitas keamanan, sementara dimensi yang lebih mendasar seperti pembangunan nilai, pemulihan kepercayaan sosial, dan rekonsiliasi budaya belum mendapat perhatian serius. Akibatnya, berbagai program tersebut sering kali gagal menyentuh akar permasalahan, yaitu keretakan relasi sosial dan defisit kepercayaan antara masyarakat Papua dan negara.
Di sisi lain, sebagian lembaga masyarakat sipil lokal juga belum mampu memainkan peran transformatif secara konsisten. Banyak di antara mereka terjebak dalam retorika politik identitas dan narasi “pembelaan terhadap rakyat,” namun enggan menyentuh kenyataan yang lebih kompleks: bahwa sebagian masyarakat Papua turut terlibat dalam lingkaran kekerasan dan perlu diajak dalam proses refleksi bersama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa baik pendekatan negara maupun masyarakat sipil masih berjalan di permukaan, belum menyentuh tataran kesadaran kolektif yang diperlukan untuk membangun perdamaian berkelanjutan.
Dari Rekomendasi ke Kesadaran Kolektif
Penanganan konflik di Papua membutuhkan revolusi kesadaran sosial, bukan hanya kebijakan politik. Perdamaian sejati tidak bisa diimpor dari Jakarta atau didikte oleh lembaga internasional, melainkan harus tumbuh dari kesediaan rakyat Papua sendiri untuk berhenti membalas kekerasan dengan kekerasan.
Beberapa langkah strategis yang dapat menjadi titik awal antara lain:
- Revitalisasi Pendidikan Perdamaian di Komunitas Lokal
Program seperti Peer Mediation, sekolah damai, dan forum rekonsiliasi adat perlu dikembangkan di sekolah, gereja, dan kampung. - Peran Gereja dan Tokoh Adat sebagai Agen Transformasi Sosial
Gereja tidak boleh hanya menjadi “penyaksi penderitaan,” tetapi fasilitator dialog lintas identitas dan politik. - Membangun Keadilan Restoratif di Tingkat Kampung
Menghidupkan mekanisme adat dan lokal untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, di luar pendekatan hukum formal. - Mendorong Kepemimpinan Moral dari Dalam Masyarakat
Elit politik dan sosial di Papua perlu memberi teladan berani untuk menolak kekerasan, meski itu berarti kehilangan dukungan politik sesaat.
Menyembuhkan Papua dari Dalam
Perdamaian yang sejati dan berkelanjutan di Tanah Papua tidak akan pernah lahir apabila semua pihak terus menunggu perubahan datang dari luar. Sejarah telah membuktikan bahwa intervensi eksternal—baik melalui kebijakan negara, bantuan internasional, maupun tekanan politik—tidak akan efektif tanpa adanya kesadaran, rekonsiliasi, dan inisiatif yang tumbuh dari dalam masyarakat Papua sendiri.
Rakyat Papua memiliki kekuatan besar untuk memutus lingkaran kekerasan yang telah membekas selama beberapa dekade. Mereka bukan sekadar korban dari konflik berkepanjangan, tetapi juga subjek aktif dan agen perdamaian yang memiliki kapasitas untuk memulihkan hubungan sosial di komunitasnya. Proses penyembuhan ini membutuhkan keberanian moral untuk mengakui luka, memaafkan, serta membangun kembali kepercayaan di antara kelompok yang selama ini terpisah oleh trauma kolektif.
Papua tidak membutuhkan belas kasihan, melainkan kesadaran baru — bahwa keberanian sejati tidak terletak pada melawan dengan kekerasan, tetapi pada kemampuan untuk berdamai dengan hati yang terluka. Dalam konteks ini, penyembuhan Papua harus dimulai dari dalam: dari hati, dari kesadaran, dan dari keberanian kolektif rakyat Papua (OAP) untuk memilih jalan damai di tengah luka yang belum sepenuhnya sembuh.
Sebagai bagian dari kekuatan sosial dan spiritual yang berpengaruh, gereja-gereja dan agama-agama lain di Papua memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung proses penyembuhan batin ini. Gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang penyembuhan, tempat di mana kasih, pengampunan, dan solidaritas dapat tumbuh. Dengan mendampingi OAP dalam perjalanan rekonsiliasi, gereja turut meneguhkan bahwa perdamaian sejati berawal dari keberanian untuk menyembuhkan luka dari dalam.
Simpulan
Kini saatnya pendekatan penanganan konflik di Papua tidak lagi berhenti pada tataran wacana, rekomendasi, dan forum konferensi, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata yang berorientasi pada pemulihan nilai kemanusiaan. Pemerintah, lembaga keagamaan, tokoh adat, dan masyarakat sipil perlu bergandengan tangan membangun kembali jembatan kepercayaan yang selama ini terkoyak oleh kekerasan dan saling curiga.
Papua tidak akan pernah mencapai kedamaian sejati selama kekerasan masih dianggap sebagai cara untuk membela martabat. Perdamaian sejati hanya dapat tumbuh ketika masyarakat bersedia melepaskan dendam dan memilih jalan dialog yang jujur dan setara. Perubahan sejati tidak datang dari kekuatan senjata atau tekanan kebijakan, melainkan dari kesadaran kolektif untuk menghentikan siklus kebencian.
Ketika masyarakat Papua berani berkata, “Kami tidak ingin hidup dalam kebencian lagi,” maka itulah titik awal dari rekonsiliasi sosial dan penyembuhan batin yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, keterampilan mendengar aktif memiliki peran strategis — bukan hanya sebagai teknik komunikasi, tetapi sebagai pondasi etis dan moral bagi proses transformasi menuju Papua yang damai, adil, dan manusiawi.